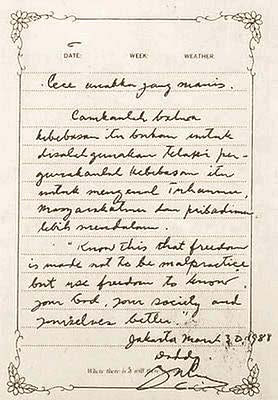Sopir taksi yang mengantar saya pulang dari kerja pada suatu sore mengeluh kepada saya, mengapa pada era reformasi ini masyarakat justru semakin miskin, sementara di sisi lain para pejabat justru semakin mementingkan diri sendiri. Bapak pengemudi taksi ini menunjuk sederet kasus seperti mahalnya harga kebutuhan pokok, naiknya harga BBM, meningkatnya biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang makin tak terjangkau. Sementara itu di sisi lain, para pejabat sibuk menaikkan pendapatan untuk dirinya sendiri. Jika demikian, ia menganalisis, gerakan reformasi yang dicanangkan mahasiswa dulu nyaris tak memberi arti apa-apa.
Merenungkan kembali omongan supir taksi itu, saya jadi teringat teori konsolidasi demokrasi. Menurut teori ini, suatu momentum gerakan perubahan ke arah demokrasi selalu memunculkan keadaan transisi, yaitu waktu yang sangat penting yang dapat membuat momentum perubahan ke arah situasi demokratis atau pun justru kembali ke sistem otoritarianisme. Masa transisi ini bisa pendek atau panjang, tergantung dari tarik menarik kekuasaan antara kelompok prodemokrasi dan kelompok yang ingin kembali ke arah status quo. Satu hal yang menentukan dalam proses transisi demokrasi adalah masa awal transisi, apakah gerakan prodemokrasi mampu menjadi pengendali perubahan atau tidak.
Dalam kasus di Indonesia, hal ini tidak terjadi. Gerakan civil society yang dipelopori kalangan kampus dan LSM waktu itu tidak cukup ngotot untuk melakukan perubahan secara radikal. Mereka sudah cukup puas manakala Soeharto lengser dan rezim berganti.
Dengan demikian, awal transisi demokrasi di Indonesia berbeda jauh dengan people power-nya Filipina yang menjungkalkan kekuasaan presiden Marcos. People power Filipina yang berlangsung tahun 1986 lebih mampu memberi ruang peralihan kekuasaan pada kekuatan baru. Pemimpin oposisi di Fipilina saat itu, Corazon Aquino, mampu merebut posisi menjadi presiden dan mengakomodasi momentum perubahan dengan memasukkan orang-orang dari kalangan oposisi dalam jajaran kabinetnya.
Selain itu, kelompok-kelompok oposisi di Indonesia waktu itu tidak cukup kompak menelurkan agenda reformasi yang diinginkan. Akibatnya, sampai saat reformasi telah berjalan satu dekade, masa transisi menuju demokrasi masih belum menemukan mata rantai pijakan yang mantap.
Dalam kerangka teori ini, situasi chaos sangat mungkin terjadi. Mengingat dalam masa transisi seperti ini, ketatanegaraan masih uji coba. Peraturan perundang-undangan masih belum menjadi koridor baku, serta penegakan hukum masih bergantung pada kemauan politik elit. Dengan demikian, nasib supir taksi tadi, kita dan berjuta rakyat lainnya sangat bergantung pada relasi kekuasaan antarkelompok kepentingan yang ada.
Kalau dipetakan secara sederhana, saat ini ada dua kelompok besar yang bermain di gelanggang kekuasaan. Kelompok pertama adalah kelompok pro status quo, yaitu orang-orang yang tidak mau berubah karena melihat bahwa perubahan sistem bakal menggerus kekuasaannya. Kelompok kedua adalah kelompok pro perubahan, yang melihat bahwa sistem ketatanegaraan di negeri ini harus diubah menjadi sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel.
Di panggung politik Indonesia, tarik menarik antara kedua kelompok ini riil terlihat, baik dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dalam implementasinya maupun dalam penegakan hukumnya.
Peraturan perundang-undangan sering kali sulit dipakai sebagai aturan main karena peraturan dibuat demi kepentingan sekelompok elit tertentu. Kasus pembuatan PP 37/2006 tentang tunjangan komunikasi intensif dapat menjadi contoh yang baik. Setelah banyak anggota DPR yang terjerat kasus korupsi karena penyalahgunaan alokasi anggaran DPRD, PP 37/2006 dianggap sebagai pintu keluar untuk menghindarkan mereka dari jeratan hukum. Untuk kasus ini, tidak ada cara lain bagi kelompok pro reformasi untuk mengadvokasi kecuali dengan gerakan protes untuk membatalkan peraturan perundang-undangan.
Hambatan tidak berhenti pada peraturan saja. Ketika peraturan telah mengakomodasi prinsip demokrasi, tidak jarang hal itu dihambat dari teknis pelaksanaannya, misalnya saja dalam sistem pemilihan kepala daerah (pilkada). Di satu sisi, pilkada diakomodasi untuk mendorong agar sistem politik lebih akomodatif bagi suara rakyat untuk menentukan kebijakan. Dengan pemilihan langsung diharapkan akan ada kontrak langsung antara kepala negara dan kepala daerah dengan rakyat, sehingga ada dorongan bagi para pemimpin untuk mengabdi pada kepentingan rakyat. Meski demikian, mekanisme ini tidak berjalan mulus dalam praktiknya. Ada kepentingan lain yang menyabot mekanisme kontrak langsung antara kepala daerah dan massa pemilihnya. Misalnya saja, dilarangnya calon independen. Peraturan perundang-undangan mengharuskan seorang kandidat kepala daerah untuk mencalonkan diri melalui partai politik yang memenuhi syarat. Dengan demikian, peraturan ini telah menyabot kepentingan rakyat pemilih, karena dengan aturan ini kandidat kepala daerah akan lebih memperhatikan kepentingan partai politik daripada kepentingan rakyat pemilih.
Selain kendala dari sisi regulasi, kendala dari segi budaya juga masih terlihat dalam proses demokratisasi di tingkat lokal ini. Meskipun mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung dan kepala daerah tidak dapat diberhentikan oleh DPRD, tapi masih saja marak adanya resistensi terhadap perubahan mekanisme ini. Di beberapa daerah, kepala daerah yang dianggap tidak kompak atau tidak disukai oleh partai-partai yang berkuasa, dicoba untuk didongkel dari kedudukannya. Misalnya hal yang sempat terjadi di Depok dan Banyuwangi pada beberapa tahun silam.
Dengan kekosongan peraturan perundang-undangan, sementara penegak hukum yang ada juga sangat lemah, akibatnya dalam kasus-kasus semacam ini antara satu kelompok dengan kelompok yang lain bermain pada tataran di luar koridor hukum. Kelompok satu dengan kelompok lain saling membentuk kelompok penekan untuk memprotes kelompok lain.
Dalam situasi ini ada beberapa cara untuk memperkuat daya tawar rakyat. Yang pertama adalah memperkuat lembaga kepresidenan. Presiden yang telah dipilih secara langsung oleh rakyat harus diperkuat kelembagaannya sehingga mampu berjalan efektif untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melayani kepentingan rakyat. Selama ini lembaga kepresidenan tampak lemah, karena meski presiden dipilih langsung oleh rakyat namun ia harus mengakomodasi kepentingan partai politik di parlemen. Akibatnya, dalam banyak kasus, pemerintah sangat akomodatif terhadap kepentingan lembaga legislatif.
Yang kedua adalah dengan mengubah sistem pemilihan legislatif dari sistem campuran antara distrik dan proporsional menjadi sistem distrik. Dengan sistem pemilihan model distrik, calon anggota legislatif akan dipilih langsung oleh rakyat, sehingga mau tidak mau harus mementingkan kepentingan rakyat. Selama ini sistem campuran tidak mengubah kebancian sistem proporsional, yang membuat anggota legislatif lebih mementingkan kepentingan partai ketimbang konstituen.
Yang ketiga adalah memperkuat kontrol masyarakat terhadap penyelenggara negara. Demi kepentingan ini, maka lembaga-lembaga non pemerintah, pers dan kampus harus diberi ruang yang luas untuk mendapatkan informasi. Kelompok-kelompok inilah yang mampu menyuarakan kepentingan masyarakat dan mampu memobilisasi massa untuk mendukung ataupun menolak suatu kebijakan tertentu.
Thursday, May 1, 2008
Jalan Berliku Demokrasi
Posted by Cisca at 3:20 PM
Monday, March 31, 2008
G E L A R
Kontroversi tentang mensyaratkan gelar S1 untuk calon presiden membuktikan, kita umumnya masih menganggap gelar sebagai atribut penting untuk menengarai apakah seseorang memiliki bobot atau tidak. Semakin tinggi gelar akademisnya, semakin dianggap berbobot orang itu. Maka wajar kalau umumnya orang memilih mencantumkan gelar di seputar namanya. Selain gelar akademis, bahkan gelar kebangsawanan, militer, jabatan sipil atau gelar haji pun dianggap membantu memberi kemantapan. Kita kadang-kadang melihat sebuah nama yang ramai dengan berbagai atribut. Tidak cukup satu yang akademis, misalnya. Kalau dia memiliki lebih dari satu gelar akademis, bahkan yang tingkatnya lebih rendah pun disandingkan dengan gelar-gelar lain yang lebih tinggi. Salahkah?. Tentu tidak. Itu hak pemiliknya.
Tiap manusia memiliki kebutuhan psikologis yang tidak bisa diduga orang lain. Juga bergantung pada perangkat nilai masyarakat lingkungannya. Di negara maju, gelar akademis umumnya hanya dipakai untuk kepentingan profesi ---seperti gelar dokter spesialis--- atau untuk kepentingan akademis. Biasanya hanya gelar S3 yang dipasang. Penyandangnya dianggap menguasai suatu disiplin ilmu lebih dari yang lain-lain. Di Indonesia, sementara ini, gelar apapun bidang dan tingkatannya memiliki nilai lain. Inilah tahapan proses.
Kalau kita menyerahkan kartu nama tanpa gelar, adakalanya kita merasa kurang dianggap. Seakan, tanpa gelar kita tidak ada artinya. Begitu rupa, hingga ada tokoh-tokoh yang memiliki gelar palsu, atau berusaha memperoleh gelar tinggi dengan cara gampang. Dengan membayar perguruan tinggi yang membuka kesempatan, misalnya. Untuk yang bersangkutan, itu lebih baik daripada harus menghadapi masyarakat tanpa memakai gelar. Masyarakat kita memang sedang haus gelar.
Menghadapi ini, marilah jujur. Mungkinkah negara yang belum memberikan perhatian maksimal ---artinya sesuai yang diamanatkan UUD --- dibenarkan menuntut bobot pendidikan akademis yang maksimal dari warganya?. Gelar S1 sudah menjadi persyaratan memasuki lapangan kerja swasta maupun pemerintah untuk pekerjaan tingkat tertentu. Mereka yang bergelar dianggap menguasai atau---paling tidak--- mengenal disiplin ilmu tertentu. Dia juga biasa mengadakan riset, studi banding, menganalisa serta membuat kesimpulan. Wawasannya dianggap lebih luas karena luasnya pergaulan dengan orang-orang dari berbagai disiplin ilmu lainnya. Sudah dengan sendirinya ada asumsi bahwa mereka lebih berbobot dari yang tamatan SMA, yang pembelajarannya bersifat umum. Autodidak tidak masuk hitungan. Pada akhirnya menjadi hak perekrut tenaga kerja untuk membuat pilihan karena tuntutan pekerjaan yang memang sudah lain dari generasi lalu. Tetapi, apakah tamatan perguruan tinggi selalu memenuhi harapan para perekrutnya?. Itu tergantung dari perguruan tinggi yang meluluskannya dan pribadi yang bersangkutan. Juga bergantung pada kemampuan lembaga perekrut untuk membimbingnya.
Untuk kepentingan negara, dibutuhkan jauh lebih dari sekedar persyaratan standar. Mensyaratkan para calon pemimpin negara harus tamatan perguruan tinggi, rasanya tidak tepat. Seakan-akan tokoh pemimpin hanya harus disaring dari para tamatan perguruan tinggi. Diperlukan waktu bertahun-tahun untuk membentuk dan membangun kepribadian seorang pemimpin negara. Tidak harus lewat bangku kuliah. Dia terbentuk di lingkungan keluarga, masyarakatnya, lingkungan nasional dan internasional, dan partai politik yang mengawasi kaderisasinya untuk kepemimpinan.
Kalau dibandingkan dengan lamanya pendidikan di bangku kuliah, lama masa pembentukan seseorang menjadi pemimpin negara jauh lebih lama. Yang hebat di bidang akademis belum tentu berhasil menjadi pemimpin negara yang baik, walaupun tentunya ada lulusan perguruan tinggi yang berhasil menjadi pemimpin besar, contohnya Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka ditempa oleh masa revolusi yang lama, ketika Indonesia mulai melek bahwa sudah waktunya bangkit menjadi bangsa yang merdeka. Dua tokoh itu dan beberapa tokoh muda lainnya, berhasil menghadapi tantangan bangsanya untuk memerdekakan diri.
Ide mensyaratkan pendidikan S1 untuk calon presiden saat ini banyak ditentang karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan, ditinjau dari segi sosial maupun politik. Ketika masyarakat meneriakkan soal krisis kepemimpinan, soal langkanya para pemimpin bangsa yang mumpuni, tiba-tiba muncul saran tentang persyaratan yang mereka rasakan tidak relevan untuk saat ini. Tidak untuk saat ini karena yang penting sekarang bukan pemimpin yang bergelar, melainkan yang mampu memimpin.
Mengapa pada saat ini timbul saran itu?. Yang bisa menganalisa dan menjawab adalah partai-partai politik, karena merekalah yang melakukan kaderisasi untuk pemimpin-pemimpin di negeri ini. Mereka pula yang bertanggung jawab mengenai bobot para calon pemimpin yang akan mereka usung untuk memimpin negeri ini. Saran persyaratan S1 mungkin menuju sasaran seputar itu.
Posted by Cisca at 9:14 AM
Thursday, December 27, 2007
Manusia dan Alam
Sedang mengalami ketidakseimbangan ekosistem yang relatif parah, sehingga manusia dan alam berada pada posisi yang berlawan-lawanan. Ketidakseimbangan ekosistem inilah yang diistilahkan dengan Bencana Alam. Inilah kondisi global di negeri ini terkait dengan fakta alamnya.
Berbagai perspektif muncul dalam rangka memahami makna terminologi alam ini. Satu diantaranya dari perspektif teologi. Satu tema besar dalam teologi adalah seputar proses terciptanya alam semesta. Kepercayaan akan adanya eksistensi Tuhan membawa konsekuensi logis bahwa alam semesta merupakan bagian dari proses sebab akibat dan Tuhan adalah penyebab awal yang mengakibatkan terjadinya alam semesta. Keberadaan Tuhan tidak disebabkan eksistensi lain yang mendahuluinya (prima causa). Para teolog sepakat dalam persoalan itu.
Perbedaan pandangan mulai muncul dalam dunia teologi menyikapi pascapenciptaan alam oleh Tuhan. Sebagian kalangan berpandangan bahwa setelah diciptakan secara mutlak, Tuhan tidak ikut campur (intervensi) terhadap segala proses yang terjadi di dalamnya. Alam semesta ini berjalan dengan hukumnya sendiri atau juga diakibatkan tindakan yang dilakukan para penghuninya (manusia juga hewan). Konsep ini melahirkan pandangan tentang kebebasan manusia, bahwa manusia memiliki kebebasan penuh untuk melakukan tindakan yang diinginkannya tanpa ada intervensi dari Tuhan (free will and free act).
Muncul kelompok dengan pandangan yang bertolak belakang, yang menyimpulkan bahwa segala fenomena yang terjadi di alam semesta pascapenciptaannya berada di bawah kendali dan kreasi Tuhan, merupakan refleksi dari Kehendak dan Tindakan Tuhan. Gagasan ini mendasari lahirnya konsep Fatalisme.
Di antara dua konsep ekstrem itu muncul pandangan lain yang mencoba menengahi. Menurut aliran jenis ini, pascapenciptaan alam semesta, Tuhan tidak sepenuhnya tidak mengintervensi proses yang terjadi di dalamnya, namun juga tidak sepenuhnya mengendalikannya. Dalam batas dan kondisi tertentu, Tuhan mengintervensi proses alamiah, yang berarti juga campur tangan terhadap kemutlakan Kebebasan Manusia. Dengan konsep ini, manusia tidak sepenuhnya dapat merealisasikan kehendak dan tindakannya, tapi tidak juga dikekang tanpa ruang ekspresi.
Ketiga pandang teologi ini kemudian ikut memberi andil bagi terbangunnya perspektif dan interpretasi yang berbeda-beda tentang fenomena alam, khususnya bencana. Pandangan teologi yang meneguhkan Kebebasan Manusia secara penuh membentuk paradigma yang berpandangan bahwa semua fenomena yang mencuat di muka bumi ini dapat dicari rasionalitasnya pada kerangka hukum kausalitas. Hipotesis bagi terjadinya bencana alam merupakan sebab dari akibat yang dilakukan oleh tangan manusia. Karena manusia memainkan peran sepenuhnya dalam eksistensi alam, maka manusia bertanggung jawab sepenuhnya.
Teori fatalistik justru mengedepankan peran Tuhan dalam berbagai proses kehidupan dan fenomena alam. Bencana alam dipersepsikan sebagai akibat dari tindakan Tuhan, sebagai penyebabnya. Dalam hal ini manusia hanyalah mediator bagi terwujudnya kehendak Tuhan, oleh karenanya secara konstitusional manusia tidak memiliki tanggungjawab apapun terhadap segala fenomena dan bencana alam yang terjadi.
Konsep yang cenderung menengahi dua titik ekstrim itu beranggapan bahwa bencana alam bisa merupakan akibat dari tangan manusia dan sekaligus hasil kreasi takdir Tuhan. Kebebasan manusia dikombinasikan dengan Kehendak Tuhan tanpa mempertentangkan keduanya. Tanggungjawab yang dipikul tidak sepenuhnya berada di pundak manusia dan tidak pula dianggap bukan tanggung jawab manusia. Inilah yang memunculkan persepsi bahwa bencana alam adalah teguran dari Tuhan atau ujian bagi kesadaran manusia.
Dari tiga jenis pandangan itu, mayoritas masyarakat Indonesia lebih dekat dengan corak ketiga. Yang cenderung lebih moderat namun berimbas pula pada rendahnya tanggungjawab manusia yang terkait dengan eksistensi alam dan segala fenomena yang terjadi di atasnya. Pada saat yang sama, segala bencana alam itu dipersepsikan sebagai akibat dari ulah tangan manusia, namun pada saat yang sama dapat dipersepsikan sebagai Kehendak Tuhan.
Posted by Cisca at 3:30 PM
Tuesday, December 25, 2007
Mawar Natal
 Kasih sayang membuat bumi berputar, Love Makes The World Go Around. Love bisa diartikan kasih sayang "antarmanusia". Seandainya bumi tidak mengenal konflik, permusuhan dan kekerasan tapi hanya mengenal kasih sayang, saling pengertian dan tolong menolong, alangkah bahagianya manusia di bumi. Bagi kita umumnya, Mawar Natal bisa ditafsirkan sebagai simbol harapan itu. Memang baru berupa harapan, karena kita masih akan menghadapi tahun baru yang penuh ketimpangan dan ketidakserasian, baik hal antarnegara atau bangsa maupun antarwarga kita sebagai suatu bangsa. Makin menipisnya sumber bumi dan berjubelnya penduduk dunia menyebabkan orang menjadi ribut berebut demi kepentingan masing-masing.
Kasih sayang membuat bumi berputar, Love Makes The World Go Around. Love bisa diartikan kasih sayang "antarmanusia". Seandainya bumi tidak mengenal konflik, permusuhan dan kekerasan tapi hanya mengenal kasih sayang, saling pengertian dan tolong menolong, alangkah bahagianya manusia di bumi. Bagi kita umumnya, Mawar Natal bisa ditafsirkan sebagai simbol harapan itu. Memang baru berupa harapan, karena kita masih akan menghadapi tahun baru yang penuh ketimpangan dan ketidakserasian, baik hal antarnegara atau bangsa maupun antarwarga kita sebagai suatu bangsa. Makin menipisnya sumber bumi dan berjubelnya penduduk dunia menyebabkan orang menjadi ribut berebut demi kepentingan masing-masing.
Toh, kita harus bersyukur. Paling tidak, ada niat membangun kerukunan dalam masyarakat kita. Simbol ini indah dan menyejukkan. Bahwa ada berita penyimpangan, anggap saja itu dilakukan oleh sekelompok kecil orang yang tidak mengerti. Maafkan mereka yang tidak mengerti.
Ada ungkapan syair,
Another X-mas, another year
another crisis in the gulf...
Yet another chance
If not to change the world
to love it more...
Life is a gift
Bagaimana kita menafsirkan maknanya, kita masing-masing bebas menerjemahkannya. Saya menafsirkannya sebagai kesadaran akan kelemahan manusia bahwa dia tidak bisa mengerti makna kebesaran hidup, karena itu manusia akan berulang membuat kesalahan yang sama. Tetapi setiap datang tahap baru kehidupan, paling tidak ada niat untuk memperbaikinya, karena manusia mencintai hidup yang memang merupakan karunia dari Tuhan.
Tentu kita berharap hidup di tahun baru tidak hanya membawa impian kosong yang membangkitkan keputusasaan dan amarah, yang membangkitkan sikap saling curiga dan saling menyalahkan. Artinya, yang terjadi sering tidak sama seperti yang diharapkan. Pada saat kepandaian, kemampuan dan kebijaksanaan sudah dapat dimanfaatkan untuk menyusun strategi demi kehidupan yang kebih baik, kita sering mengabaikan kesempatan itu. Inilah tragedi yang seringkali datang berulang.
Pada tahun-tahun yang akan datang, kemungkinan besar masih akan kita saksikan retorika tuduh menuduh bombastis antara negara-negara kaya dan yang miskin, maupun antara masyarakat kaya dan miskin di suatu negara. Kemiskinan bisa memperkeruh sentimen antaragama.
Kemunafikan pun sebenarnya menghalangi terbangunnya kehidupan yang lebih baik. Di negara-negara berkembang sendiri terdapat kepincangan antara rakyat banyak -- yang mewarisi kemelaratan dari generasi ke generasi -- dengan kelompok kecil elite yang penghidupannya lebih baik dan dianggap memegang kendali di bidang pemerintahan, swasta atau bahkan di bidang sosial dan agama. Kelompok kecil ini dianggap tidak merasa untuk bergegas mengadakan perubahan radikal demi kesejahteraan bersama, walaupun mungkin cukup galak meneriakkan tuntutan kepada negara-negara kaya.
Mungkin memang perlu diadakan tata ekonomi dan sosial baru yang lebih memberi kesempatan kepada yang miskin di sebuah negara, lewat kepedulian maupun pemerataan penghasilan dan kekayaan negara. Di Indonesia, ini berarti lebih mengonsentrasikan usaha dan sumber-sumber pada bidang pertanian dan pembangunan pedesaan, meningkatkan industri kecil yang memberikan penghasilan memadai untuk rakyat kecil dan landreform yang kebijakannya sebenarnya sudah dicanangkan oleh pemerintah.
Mawar Natal adalah simbol harapan untuk kebersamaan, ungkapan simpati dan juga ajakan. Yang pasti, ia berusaha menyuarakan sesuatu yang positif untuk kesejahteraan batin semua pihak. Ini dibutuhkan untuk awal menggerakkan rasa kesetiakawanan antarwarga. Sebuah langkah kecil menuju persahabatan dan kerjasama demi kemaslahatan bersama. Semoga.
Posted by Cisca at 12:15 AM
Friday, November 9, 2007
Kepahlawanan
Masih adakah pahlawan di negeri kita hari ini? Masihkah ada pahlawan di tengah kebangsaan yang disebut Ben Anderson sebagai "komunitas terbayang" ini? Sejauh mana mental, perilaku, sikap dan keteladanan para pahlawan yang tidak pernah lupa kita peringati itu bisa aktual dan mengejawantah dalam kehidupan kita sehari-hari ?. Cukupkah menghormati mereka hanya dengan menundukkan kepala untuk mendoakannya? Cukupkah hanya dengan mengheningkan cipta?. Mungkin cukup, tetapi arti mengheningkan cipta bukan bagaimana kepala tertunduk belaka tanpa mengaktualkan sikap dan laku hidup.
Sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pahlawannya. Kita percaya itu, namun makna ungkapan ini bagi kita sering terlalu datar dan sering diartikan bahwa penghormatan adalah rutinitas formal saja. Apa yang telah dilakukan oleh Bung Tomo tidak hanya membela Surabaya, tapi juga kehormatan bangsa. Untuk menegakkan harkat dan martabat kebangsaan dikorbankanlah seluruh jiwa raga, walau hanya dengan kekuatan bambu runcing. Pengorbanan nyawa adalah hal kecil jika dibandingkan pelecehan harga diri bangsa.
Ironisnya, saat ini harga diri dan martabat kebangsaan sering tergadaikan oleh kepentingan pragmatis individual. Sudah jarang laku kepahlawanan dan heroisme yang termanifestasikan untuk membela kebangsaan. Kebangsaan bermartabat yang diperoleh dengan pengorbanan luar biasa itu kini mulai digerogoti oleh sikap dan perilaku yang sering bertentangan.
Saat ini kepahlawan bukan harus diteladani dengan persepsi medan pertempuran yang berdarah-darah. Heroisme itu seharusnya mendarahdaging dalam berbagai semangat untuk membela yang tertindas dan menegakkan harga diri di mata bangsa-bangsa lain.
Pelajaran pertama bagi generasi kini ialah lunturnya semangat itu di era yang serba pragmatis dan materialistis ini. Sebagian dari kita rela menjual harga diri hanya demi sesuap nasi. Jangankan mengorbankan nyawa untuk bangsa, bahkan kalau perlu uang rakyat dihabiskan demi kepentingannya sendiri. Ini pengkhianatan terhadap semangat revolusioner yang telah diperankan oleh arek-arek Suroboyo yang telah gugur membela harga diri bangsa. Mereka rela berkorban harta benda dan nyawa untuk membela harga diri. Kini, justru harga diri itu kita jual untuk mempertahankan nyawa.
Kontradiksi-kontradiksi inilah yang kerap menjadikan pembelajaran atas sikap heroisme dan patriotisme tidak memiliki artinya.
Heroisme sejarah yang membekas di hati sanubari rakyat setiap 10 November mungkin saja tak akan lapuk ditelan zaman, tapi arti penting dari semangat kepahlawanan itulah yang setiap saat akan lekang dikikis sikap yang cenderung melupakan sejarah. Apalah artinya bangsa yang melupakan sejarah?. Apa artinya bangsa yang tidak mampu mengontekstualisasikan laku kepahlawanannya?.
Begitu banyak yang lahir di negeri kita justru pahlawan yang bangun kesiangan, berteriak-teriak ketika nasi sudah menjadi bubur. Semua diorientasikan untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Berpikir jauh ke depan untuk masyarakat bangsa secara luas sudah ditinggalkan.
Semangat ini tercermin dalam cara dan sikap partai-partai yang memelihara dan mengembangkan konflik demi kepentingan dirinya sendiri. Jarang kita lihat semangat heroisme mereka untuk membela bangsa ini dari berbagai masalah. Tingkah laku elite kita justru lebih sering menambah penderitaan wong cilik. Penggusuran-penggusuran di lakukan atas bangsa yang merdeka. Tanggung jawab untuk melindungi dan menyejahterakan sudah musnah ditelan nafsu serakah dan angkara murka.
Roh para pahlawan tidak minta dihormati dengan simbol-simbol tanpa makna, keharuan dan tangis tanpa teladan. Mereka akan lebih tenang jika generasi kini memiliki sikap jujur, adil, tidak korup dan sungguh-sungguh menjaga kewibawaan bangsa.
Merefleksikan nilai kepahlawanan 10 November ini kita diajak untuk merenungkan kembali berbagai kegagalan pemerintah membawa rakyatnya sejahtera. Para pahlawan ingin negara ini mempersembahkan yang terbaik untuk rakyatnya. Bukan sebaliknya, menghisap keringat rakyat untuk kepentingan segelintir elit politik dan pemerintahan.
Posted by Cisca at 7:36 AM
Sunday, October 28, 2007
Sumpah Pemuda
Setiap tanggal 28 Oktober biasa dikenang oleh rakyat Indonesia dengan Hari Sumpah Pemuda. 79 tahun yang lalu, para pemuda dari seluruh Indonesia berkumpul dan menyatakan sumpah sebagai bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia dan berbahasa satu bahasa Indonesia. Mereka berkumpul, bersatu dan menyatukan suara sebagai bangsa Indonesia dengan dilatar belakangi penderitaan yang sama, sama-sama merasakan pahitnya menjadi bangsa yang terjajah. Pokok utama inilah yang membuat mereka sama-sama merasakan adanya kedekatan emosional, ingin bersama menjadi bangsa merdeka. Karena itu mereka bersatu, karena dengan bersatu mereka menjadi kuat. Cita-cita merekapun akan lebih bisa terpenuhi.
Sumpah Pemuda juga telah bisa membuktikan menjadi pemersatu yang sangat ampuh bagi para pemuda dalam perjuangannya melawan Belanda dan Jepang, bahkan revolusi Agustus 1945 dicetuskan dari berbagai golongan pemuda yang menjunjung tinggi sumpah pemuda.
Permasalahan perbedaan bahasa pun dapat diselesaikan dengan penerimaan para pemuda Indonesia terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu mereka. Tapi sebagai prinsip dasar pejuangan, Sumpah Pemuda bukannya tanpa cacat. Ini bisa dilihat dari saripati yang dihasilkan oleh Sumpah Pemuda yang lebih menonjolkan satu prinsip, yaitu persatuan saja. Misalnya slogan yang didengar sebagai satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, itu adalah slogan yang sangat menonjolkan prinsip persatuan. Padahal, persatuan sebagai slogan bangsa belumlah cukup menjadi perekat kuat pada suatu bangsa. Adanya persatuan bukan berarti menghilangkan skema tentang unsur hierarki sosial atau stratifikasi, karena persatuan bukanlah kesetaraan. Persatuan belum tentu menghilangkan skema tentang golongan atas dan bawah. Tidak adanya kesetaraan tentunya akan berdampak pula terhadap kehidupan berpolitik, toleransi atau intoleransi.
Ini akan jelas terlihat ketika kemerdekaan telah sama-sama direbut. Tiap golongan yang merasa berkonsep paling benar akan memaksakan konsepnya supaya dijalankan oleh pemerintahan yang baru. Kalau kita mau melihat ke belakang , sebenarnya sebelum dan sesudah Sumpah Pemuda dikumandangkan, konsep tentang negara Indonesia terpecah setidaknya menjadi dua kubu besar, yaitu dari golongan nasionalis Islam yang diusung oleh Partai Sarekat islam ( PSI ) dan golongan nasionalis sekuler yang diusung oleh Partai Nasional Indonesia ( PNI) di bawah pimpinan Soekarno.
Golongan nasionalis Islam menghendaki negara Islam dan memakai Islam sebagai undang-undangnya. Sedangkan golongan nasionalis sekuler menghendaki negara Pancasila. Bagi golongan nasionalis Islam, konsep tentang negara Islam sudah menjadi keinginan yang tertanam sejak lama. Apalagi, wilayah jajahan Belanda adalah wilayah yang mayoritas penduduknya muslim. Pendapat mereka waktu itu, kalau Indonesia merdeka tentu hukum-hukum Islam pun akan berlaku. Oleh karenanya yang dipentingkan pemimpin-pemimpin Islam saat itu bukanlah negara yang berdasarkan Islam, tetapi kemerdekaaan Indonesia. Meski pun tujuan utama dari kubu ini adalah negara Islam, namun tujuan menggapai kemerdekaan adalah menciptakan prinsip hukum yang berdasarkan Islam.
Pertentangan di antara kedua golongan itu tidak dapat dihindari. Sempat tercapai kesepakatan berupa Piagam Jakarta yang berisi tentang penerimaan golongan nasionalis Islam pada Pancasila yang akan dibentuk di dalamnya ditambahkan satu ketentuan mengenai umat Islam. Namun, kesepakatan itu tidak dibacakan oleh golongan nasionalis sekuler, sehingga pertentangan dua golongan kembali terjadi dan ada sampai saat ini.
Buruknya lagi, pertentangan yang hadir saat ini bukan hanya berasal dari konsep bernegara, bahkan juga pertikaian antar etnik, agama dan suku. Prinsip persatuan yang telah dilekatkan sejak Sumpah Pemuda pada 79 tahun yang lalu sepertinya kian pudar dan makin terkikis. Permusuhan dan perpecahan sesama bangsa sendiri mulai tampak begitu membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa kita.
Apakah ini pertanda bahwa semangat Sumpah Pemuda sudah tidak bisa lagi menjadi simbol persatuan?. Dulu, Sumpah Pemuda bisa menjadi simbol persatuan karena saat itu hanya dengan bersatulah bangsa Indonesia dapat bebas dari penjajahan, dan hal itu memang terbukti. Kini setelah musuh bersama itu lenyap, perjuangan bersama pun kian memudar. Padahal musuh bersama itu akan selalu saja muncul dengan kostum yang berbeda.
Seharusnya, untuk generasi muda saat ini, Sumpah Pemuda sebagai simbol persatuan bukan malah ditinggalkan dan dilupakan. Tapi apa yang telah diusung oleh generasi sebelumnya ditambahkan sesuatu yang kurang darinya, sehingga Sumpah Pemuda yang dulunya hanya menonjolkan persatuannya saja kini menjadi Sumpah Pemuda satu nusa, satu bangsa, satu bahasa yang bertoleransi terhadap pluralisme dan yang menghargai kebebasan hak.
Dengan demikian, Sumpah Pemuda tidak kembali berulang dari awal, tetapi menjadi dialektika yang berkelanjutan. Permasalahan disintegrasi bangsa yang ada saat ini pun dapat kembali bersatu lewat semangat Sumpah Pemuda yang baru dan segar.
Posted by Cisca at 11:30 AM
Saturday, October 13, 2007
Wednesday, October 3, 2007
Ramadhan 1428 H
Kelaparan adalah gejala kemanusiaan yang paling rendah. Lebih ironis lagi jika kelaparan ternyata menimpa sejumlah orang sedangkan yang lain menikmati kemakmuran yang melimpah. Sekarang ini, saat kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah berkembang begitu rupa, ketika paham politik dan demokrasi juga telah menjadi pilihan dan diperjuangkan dimana-mana, kelaparan dan kemiskinan sepertinya tetap mewarnai citra buruk dari peradaban umat manusia dan belum bisa terpecahkan.
Globalisasi, suatu keadaan yang dikendalikan arus pasar kapitalisme, sesungguhnya hanya bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki surplus ekonomi. Bagi mereka yang tersingkir, jangankan bisa mempunyai peluang untuk bersaing dalam mengubah nasib hidup mereka, bisa bertahan untuk hidup sehari-hari saja sudah luar biasa.
Kehidupan Ramadhan yang sedang kita jalani sekarang ini tampaknya memberikan pandangan sosial bahwa besaran jumlah orang miskin dan terancam lapar akan semakin bertambah. Walaupun menurut pemerintah makroekonomi Indonesia menunjukkan indikasi baik, hal itu tidak serta merta mencerminkan nasib dan kehidupan rakyat sehari-hari. Sejak harga BBM dinaikkan begitu tinggi, harga kebutuhan pokok semakin tidak terjangkau. Bukan sekadar soal persediaan barang di pasar, tapi daya beli yang semakin merosot. Kalau daya beli tidak ada, ya hidup menjadi semakin susah.
Jelas Tuhan tidak ingin menyiksa umat manusia dengan kewajiban melaksanakan puasa. Oleh karena itu dianjurkan agar mempercepat berbuka kalau sudah datang waktunya dan mengakhiri makan sahur sebelum waktu imsak tiba. Pada dasarnya semua bentuk ibadah ritual bagi setiap manusia haruslah menjadi mekanisme reflektif untuk meneguhkan nilai kemanusiaan yang dibawa dalam fitrahnya terus menerus. Hal ini yang menjadi cita-cita yang harus diperjuangkan tidak hanya untuk hidupnya sendiri, tapi juga kebersamaan sebagai makhluk peradaban.
Puasa dalam Islam sesungguhnya lebih dari soal perlunya manusia mencari perasaan spiritual, tapi juga perspektif ideologi sosial yang jelas, yaitu kelaparan yang terjadi karena ketimpangan sosial merupakan gejala penurunan derajat dan harkat kemanusiaan yang paling buruk. Bukan karena maunya Tuhan, tapi akibat dari sumber-sumber ekonomi hanya dikuasai sejumlah kecil orang dan sebagian besar mereka tidak mempunyai akses politik untuk mendapatkannya.
Dalam Ramadhan, bagi kita yang menjalankan ritual "lapar" selama siang memang bisa menunggu waktu kita berbuka dan makan sahur, tapi bagaimana dengan mereka yang menjadi bagian umat yang kelaparan?. Ya tentu saja mereka terus berpuasa. Mereka menunggu sampai datangnya keputusan politik yang adil agar semua karunia Tuhan yang telah dianugerahkan di bumi ini tidak hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil saja yang diuntungkan secara struktural.
Sudahkan kita secara ideologis menerima pahala puasa hanya dengan selesainya berbuka, sedangkan kesadaran keberagaman yang kita peroleh ternyata tetap tumpul terhadap kemungkaran sosial yang semakin timpang ini?.
Posted by Cisca at 9:36 AM
Monday, September 3, 2007
Harapan Kepada Dunia Pendidikan
Ada yang menarik dari catatan di bidang pendidikan. Dibilang menarik karena masih banyak kebijakan pendidikan yang tidak banyak membawa perubahan. Beberapa produk kebijakan masih tidak realistis, terlalu normatif dan masih terkesan baik di atas kertas. Namun melihat kondisi obyektif di lapangan justru kebijakan itu bersifat kontraproduktif. Contohnya kehadiran "kurikulum baru" yang disebut KTSP ( Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ).
Secara konsep kurikulum itu diakui memberikan angin segar, yaitu otonomi kepada guru dan sekolah secara akademis. Guru dan sekolah diberikan semacam kebebasan untuk meracik kurikulum yang sesuai. Disini kelak terjadi perubahan etos kerja guru, dari yang awalnya konservatif menjadi kreatif. Selanjutnya dengan model kurikulum yang dibuatnya sendiri, guru sudah seyogyanya berani meninggalkan cara-cara lama yang membuat dirinya bergantung pada petunjuk teknis ( juknis ) dan petunjuk pelaksanaan ( juklak ) proses belajar mengajar di kelas. Selain itu guru juga harus bisa mengekplorasi serta memperbaharui terus pengetahuannya sesuai anak murid yang ia hadapi. Tapi apa iya demikian adanya?
Menurut pendapat saya, penerapan kurikulum baru itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Apalagi jika syarat-syarat dasar seperti kompetensi guru dan infrastruktur sekolah tidak dipenuhi oleh pemerintah. Ada banyak sekolah yang ingin membuat kurikulum sendiri agar anak didiknya dapat mengembangkan potensinya, tapi faktor ketidaksiapan guru dan sekolah justru mengakibatkan keinginan untuk memberikan otonomi sekolah dalam menentukan materi pembelajaran yang sesuai kebutuhan dan situasi lokal, tidak bisa terwujud.
Kondisi demikian akan bertambah runyam jika pada kenyataannya banyak guru yang memiliki wawasan sempit. Apalagi jika mereka tidak ingin menerima perubahan sedikitpun. Saya sepakat dengan pendapat Prof. Soedijarto (guru besar UNJ) dan Ketua Umum Ikatan Sarjana Pendidikan (ISPI) yang mengatakan bahwa KTSP dengan kondisi saat ini baru dapat dilakukan maksimal oleh sekolah yang telah mampu, yaitu sekolah yang dari penyediaan infrastruktur termasuk buku bacaan dan internet telah lengkap. Sementara bagi sekolah yang kurang mampu, yang lazimnya terletak di daerah pinggiran kota, diduga tidak akan maksimal dalam penerapan kurikulum baru itu. Sebabnya jelas, keterbatasan infrastruktur dan minimnya kualifikasi guru. Pemerintah, dalam hal ini Depdiknas diharap agar bersungguh-sungguh mengupayakan pendanaan bagi sekolah yang kurang mampu tersebut.
Demikian juga dengan produk kebijakan pendidikan lainnya seperti UN ( Ujian Nasional ). Saya mencermati sebetulnya UN tidak mencerminkan etos belajar dan mutu pendidikan. Adanya siswa-siswa Indonesia yang berhasil meraih medali pada Olympiade Sains beberapa waktu lalu tidak bisa dijadikan inidikator bahwa mutu pendidikan kita meningkat. Lihat saja, model soal UN berupa tes pilihan ganda. Dengan model seperti itu kita tidak bisa mengukur kemampuan siswa secara komprehensif. Untuk pelajaran Bahasa Inggris, misalnya. Seharusnya yang diutamakan ialah kemampuan berkomunikasi secara lisan ( speaking ), tulisan ( writing ) dan memaknai teks ( reading ). Tapi dengan model UN berupa pilihan ganda, maka siswa cukup diajar berlatih menjawab soal selama bulan-bulan terakhir menjelang pelaksaan UN. Apakah dengan demikian sudah bisa dikatakan siswa sudah belajar keras dan mutu pendidikan menjadi lebih baik?. Apakah bukannya budaya UN justru menumbuhkan budaya instan di kalangan siswa dan guru?.
Dengan menganggap UN sebagai alat penentu kelulusan, saya berani katakan bahwa UN justru menihilkan etos kejuangan siswa ( juga guru ) dalam memahami substansi ilmu, dan menyuburkan cara-cara curang untuk mengejar angka kelulusan. Lebih jauh lagi, jika kita kaitkan dengan UU tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menyatakan bahwa standar mutu tidak bisa terpisahkan dari kompetensi lulusan, maka penyelengaraan UN inkonsistensi terhadap produk hukum tersebut. Jika mutu pendidikan hanya diukur pada ujung proses belajar siswa ( ujian ), tanpa melihat aspek secara komprehensif, kita pantas meragukan kompetensi lulusan.
Memang diakui, menguraikan persoalan UN menjadi tantangan tersendiri bagi kita, apalagi jika harus mencari penyebabnya. Tapi disini saya hanya bisa menyarankan agar pemerintah perlu membangun suasana pembelajaran yang lebih merangsang dan menantang siswa di kelas. Artinya pembelajaran difokuskan kepada proses. Kehadiran, perilaku, pekerjaan rumah (PR) dan hasil tes semua tetap diperhitungkan.
Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak siswa agar potensinya berkembang. Sekolah, sebagai pusat pembudayaan perlu menciptakan suasana pembelajaran agar siswa dapat mengembangkan potensinya. Pendidikan kita tetap didasarkan pada proses, bukan semata-mata hasil.
Terkait dengan kebijakan pendidikan, agaknya kita perlu sadar bahwa setiap penyusunan kebijakan jangan sekali-sekali mengesampingkan tata perencanaan, pembuatan program dan pendanaan. Kebutuhan pembangunan pendidikan, tidak terkecuali tingkat dasar ( SD ) perlu dihitung pembiayaannya. Kendati ada Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, namun upaya ke arah perbaikan infrastruktur belum optimal sebagaimana yang dijanjikan. Baik pemerintah pusat maupun daerah mestinya tergerak hatinya ketika menyaksikan banyaknya gedung sekolah yang ambruk. Selama ini, faktor ketiadaan sarana pendidikan tergolong kebijakan yang masih terkesan baik di atas kertas. Padahal jika ingin meningkatkan mutu pendidikan, maka persyaratan dasar seperti ketersediaan ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, laboratorium, tempat berolah raga, bermain dan sebagainya harus diwujudkan. JIka tidak, mustahil cita-cita pendidikan bermutu akan terwujud.
Terkait dengan pembiayaan, mau tidak mau anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari total APBN / APBD harus dipenuhi. Perlu kita wacanakan bahwa pendidikan adalah masalah darurat bangsa ini. Dengan kondisi saat ini, seharusnya pendidikan diposisikan pada level gawat darurat. Penyusunan anggaran pendidikan harus berpijak pada kegiatan dan kebutuhan bangsa, terutama dengan melihat prioritas bahwa pendidikan adalah kebutuhan yang mendesak.
Posted by Cisca at 11:48 AM
Saturday, July 14, 2007
Reformasi Sektor Keamanan
Bagi negara pascakonflik, reformasi sektor keamanan adalah syarat mutlak untuk konsolidasi perdamaian dan stabilitas, mengurangi kemiskinan, menegakkan hukum dan pemerintahan serta mencegah negara kembali runtuh dalam pertikaian.
Pernyataan Peter Burian (Duta besar Slovakia) untuk PBB, di hari terakhir pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Februari lalu semakin menegaskan posisi dan fenomena reformasi sektor keamanan (RSK). Sebelumnya, Sekjen PBB, Ban Ki-Moon, telah menegaskan peran PBB dalam RSK selama beberapa dekade ini, ditandai dengan kehadiran misi penjaga perdamaian di beberapa wilayah konflik.
Pandangan kedua tokoh itu memang tidak keliru. Konsep RSK sendiri memang lahir di era tahun 1990, di Eropa Timur, ketika komunis runtuh dan berbagai negara terjerembab dalam konflik internal yang berkepanjangan. Slovakia sendiri merupakan salah satu korban tersebut, yang berujung dengan perpisahan dari Negara Ceko. Jadi, RSK diharapkan menjadi pilar yang dapat merajut kembali puing-puing kehancuran yang berserakan.
Kendati konsep dan definisi RSK terus berubah dengan dinamis, namun PBB telah menetapkannya sebagai mekanisme utama dalam pengentasan wilayah konflik. Hal ini tentu mudah dipahami dan sangat beralasan. Terjerumusnya negara dalam konflik internal menandakan bahwa sistem keamanan yang digunakan selama ini mandul. Oleh sebab itu sangat logis bila sistem pada sektor reformasi keamanan tersebut harus direformasi.
Pertanyaan yang menyeruak kemudian adalah, perlukah RSK diberlakukan di negara yang tidak mengalami konflik?. Jawabannya tentu bisa beragam. Namun bila menilik konsep PBB, tentu kita telah mengetahui jawabannya. Lagipula, sebuah sistem yang belum terbukti kelemahannya, mengapa harus diperjudikan dengan sebuah sistem yang diadopsi hanya karena sedang menjadi tren?.
PBB telah memberikan landasan bagi penerapan RSK. Kriteria yang terpenting adalah wilayah konflik, harus diprakarsai oleh negara bersangkutan, bersifat kontekstual sesuai situasi dan kebutuhan. Jadi penerapan RSK tidak boleh semata-mata hanya mengikuti tren yang sedang berkembang. Apalagi bila harus melanggar paradigma dan konstitusi yang berlaku.
Bila mengacu pada premis ini, penerapan RSK di Indonesia memang tidak diperlukan, karena:
1. Indonesia bukan wilayah konflik.
2. Sistem keamanan yang ada dan merupakan hasil reformasi terbukti dapat diandalkan serta berfungsi baik. Buktinya, persoalan terorisme dapat diatasi dan berbagai konflik horizontal dapat ditangani dengan baik.
3. RSK yang coba diadopsi melalui RUU Keamanan Nasional justru merambah ketentuan UUD 1945 serta paradigma reformasi. ( Dalam UUD 1945 hasil amandemen dengan tegas memisahkan fungsi kemanan dan pertahanan. Bahkan UUD 1945 pun tidak mengenal konsep Keamanan Nasional. Selain itu, RSK yang dilakukan justru tidak seiring dengan derap paradigma reformasi yang dikibarkan. Ini terbukti dengan berbagai UU produk reformasi yang akan dianulir oleh RSK ini ).
4. Secara prinsip RSK adalah sebuah wahana menuju masa depan untuk meninggalkan kegetiran masa lalu. Bukan sebaliknya, membawa kita surut kembali ke masa silam yang traumatis. ( Namun RSK yang ingin diterapkan melalui RUU Keamanan Nasional, yang bertentangan dengan semangat UUD 1945 hasil amandemen dan paradigma reformasi justru menyenandungkan kembali luka lama dan menambatkan kita ke masa lalu ).
5. RSK sejatinya merupakan bagian dari gerbong demokrasi, untuk menggantikan sistem lama yang otoritarian dan represif. ( Oleh sebab itulah RSK diperkenalkan di saat runtuhnya negara-negara komunis dan menginjeksi sistem demokrasi. Tidak heran bila roh utama RSK---yang membedakannya dengan pola lama--- adalah nafas demokrasi yang ditawarkannya. Degup demokrasi tu tercermin dari adanya human security yang menyangkut kesejahteraan. Justru konsep keamanan produk reformasi dan amandemen UUD 1945 yang sekarang berlaku ini adalah cerminan dari RSK itu. Human Security yang menjadi ikon RSK telah termanifestasikan dalam paradigma baru Polri, perpolisian masyarakat, yang bertujuan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat ).
6. Dalam buku Security Sector Reform and Post-Conflict Peace Building yang diterbitkan oleh PBB, Ehrat dan Schnabel menyatakan bahwa prinsip yang membedakan RSK dengan pola keamanan tradisional adalah kesejahteraan dan supremasi sipil. Untuk melindungi dan mengamankan hak politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, penegakan hukumlah yang lebih mengemuka.
Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Ehrat dan Schnabel tentang RSK, sejatinya telah diemban dengan baik oleh fungsi Polri saat ini dalam sistem keamanan yang telah ada. Ini terbukti dengan fungsi Polri sebagai penegak hukum dan Polri yang telah bertransformasi menjadi institusi sipil.
Jadi, kita memang tidak perlu berjudi. Ingin keluar dari konflik justru dapat terbenam dalam konflik.
Ironis.
Posted by Cisca at 4:35 PM