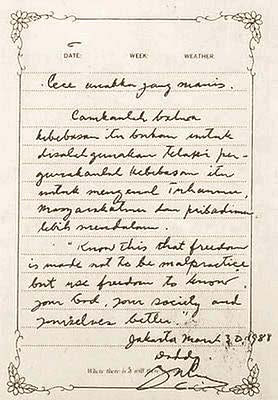"Kring..kring..kring..., suara bel sepeda Phoenix buatan Taiwan itu membelah panasnya Jakarta di sebelah barat dan kota. Sarman, si pemilik sepeda itu, ringan saja mengayuh tunggangannya melawan arah. Kadang "nyalib" di depan kendaraan lain yang melaju kencang. Raungan klaksonpun bersahutan mewakili kekesalan pemilik kendaraan lain. Peluh bercucuran dari wajah pak Sarman yang terlihat lebih tua dari umurnya yang sebenarnya.
Namun suara klakson kendaraan lain tak membuat pak Sarman grogi, tetap santai dia mengayuh pedal sepedanya. Lewat kayuhan sepedanya inilah pak Sarman menyambung hidup keluarganya. Pria berusia 42 tahun ini adalah salah seorang pengojek sepeda yang kini masih banyak di kawasan Jakarta Kota. Bahkan menjadi tunggangan alternatif yang tak lekang oleh panas hujan dan tak lapuk oleh kenaikan harga bahan bakar minyak. Habis mau bagaimana lagi ?. Berjalan kaki ke tempat beraktivitas pasca kenaikan BBM ?. Apa Mungkin ?. Lihatlah bagaimana kondisi trotoar di negeri ini. Trotoar bukan lagi untuk pejalan kaki, tapi sudah dimonopoli oleh pengendara motor dan pedagang kaki lima. Belum lagi kondisinya yang tidak terawat, masih banyak terdapat kawat bekas galian, berlubang-lubang tidak rata dan ditumbuhi pepohonan yang akarnya kadang menyandung para pejalan kaki. Belum lagi galaknya pengendara motor yang jika mereka melajukan motornya di atas trotoar, lantas ada pejalan kaki yang dianggap menghalangi jalan mereka, mereka akan membunyikan klaksonnya, mempelototkan mata sambil mengumpat, Woi, minggir!. Nggak ngeliat apa lu!". (Minggir?. Lha mau minggir ke mana lagi. Trotoar kan tempat kami berjalan kaki?. Apa kami mesti turun ke bahu jalan untuk berjalan?. Yah, terpaksalah daripada saling ngotot, ngeyel, dan memang akhirnya hanya itulah yang bisa kami lakukan. Berjalan kaki di bahu jalan raya sambil mangkel di hati pula. Kadang masih juga beresiko keserempet oleh sliwerannya kendaraan umum seperti metro mini, kopaja, mini angkot dan pengendara lainnya. Belum lagi kami harus berjalan menghindar dari kerumunan para pedagang buah-buahan dan kaki lima lainnya yang ikut meramaikan suasana pertrotoaran disini. Aduh....)
Lain halnya dengan pak Sarman yang satu ini. Keluwesannya mengendarai sepedanya menembus semrawutnya lalulintas merupakan alasan mengapa masyarakat masih setia memilih angkutan tradisional ini. Bahkan pak Sarman telah mempunyai pelanggan tetap yang menggunakan jasanya usai jam kantor. Bersama sekitar 60 orang rekan-rekannya, pak Sarman menunggu penumpang dengan sabar di depan Stasiun Kereta Api Beos , Kota.
"Saya sudah tujuh tahun ngojek sepeda" katanya. Sebelum menjadi pengojek, pak Sarman mengaku pernah bekerja di berbagai toko dan pabrik di ibukota, namun ketidaksenangan diperintah oranglain membuatnya banting setir. Awalnya menjadi pengojek sepedapun gara-gara tetangganya menawari untuk membawa sepeda yang tidak dipakai lagi. "Yah..akhirnya keterusan sampai sekarang," katanya lagi sambil tertawa terkekeh mengusap peluh di dahinya.
Yang tidak bisa disembunyikan adalah guratan wajahnya yang seolah menjadi bukti kerasnya perjuangan hidup.
Soal penghasilan, pak Sarman menuturkan, "Yah...lumayanlah bisa mendapatkan 15 ribu sampai 20 ribu rupiah sehari, karena tidak dibebani setoran. Kalau pengojek lain yang masih dibebani setoran, harus menyisihkan sejumlah 15 ribu hingga 20 ribu rupiah kepada pemilik. Ini sepeda Phoenix saya beli seharga 300 ribu rupiah, kalau yang baru sih bisa sampai 500 ribu rupiah," katanya sambil menunjuk sepedanya yang telah dilengkapi jok tambahan itu.
Karena menjadi pihak yang lemah, daya tawarpun rendah. Sulit bagi mereka mematok harga. Nominal Rp.1500,- dianggap layak untuk berjalan dari Stasiun Kereta Api Beos menuju kantor pos yang berjarak sekitar 300 meter. Namun tak jarang pula, seberapapun uang yang diberikan penumpangnya mereka terima dengan ikhlas.
Kendati minim dalam penghasilan, mereka tidak minim dengan kebaikan. Bahkan persainganpun disikapi dengan bijak. Tenggang rasa menjadi sebuah keharusan ketika melihat ada teman yang belum mendapat penumpang. Mereka sadar betul bahwa rejeki itu sudah ada yang mengatur. Untuk apa saling sikut jika hanya menimbulkan penderitaan yang berujung pada ketidaknyamanan dalam hidup dan bertambahnya musuh ?.
Meski tidak semua pengojek sepeda memiliki sifat seperti pak Sarman ini, namun ada kesamaan yang tidak bisa hilang dari mereka, yaitu komunitas marjinal. Namun rasa "nrimo" lah yang membuat kaum terpinggirkan ini menjadi "survive". Setelah merasa cukup, tidak ada lagi niatan untuk merebut milik orang lain.
Saat ini ojek sepeda hanya ada di kawasan Jakarta Utara dan Kota. Mereka para pengojekpun menjadi fasih dengan perkembangan yang ada di wilayah itu, bahkan mereka sekaligus berfungsi sebagai pemandu wisata di kawasan yang memang terkenal dengan kota tua yang banyak peninggalan bangunan bersejarahnya. Dengan uang sekitar 20 ribu rupiah, kami bisa diajak berkeliling kota. Mulai dari Stasiun kota, Museum Sejarah Jakarta, hingga ke pelabuhan Sunda Kelapa, sambil dengan senang hatinya mereka menceritakan sejarah bangunan-bangunan yang ada di sekitar situ. Akan lebih menyenangkan lagi jika hal ini dilakukan pada malam hari, setelah terik matahari Jakarta terganti oleh semilir angin laut.
Kehidupan kadang terasa tidak berubah. Kala senja menyisir pantai teluk Jakarta, pak Sarmanpun dengan bersenandung lirih--entah lagu apa yang dinyanyikannya--membelokkan setang sepedanya ke rumah, menemui anak dan istrinya. Masih tampak sesungging senyumnya karena mengantongi hasil tetesan keringat yang diperolehnya seharian. Sembari berdoa pada Sang Khalik, "Tuhan, berilah kesempatan pada saya untuk bisa berbuat baik dan menjadi lebih baik lagi"
(Ah, sebait doa sederhana dari pak Sarman dan rekan-rekannya, yang masih sawang sinawang dengan koor serempak para anggota DPR ketika menerima tambahan tunjangan sepuluh juta rupiah, di tengah duka abadi karena naiknya harga bahan bakar minyak di negeri ini), terdengar jelas sampai kami kembali membuka hari esok.
Sunday, October 30, 2005
Yang Masih Tercecer
Posted by Cisca at 5:29 PM
Tuesday, October 25, 2005
Tigaperempat Bulan Satu Perenungan
 Memasuki bulan Ramadhan ini , kita mempunyai suguhan istimewa yang mendahului sahur pertama untuk berpuasa. Yaitu "hidangan" teror bom dan bahan bakar minyak. Hal yang pertama, selain mengundang perhatian dari seluruh kalangan dunia, juga menimbulkan anggapan pada masyarakat luas bahwa negeri kita adalah lahan bagi hidupnya satu bangsa yang telah disarangi kelompok teroris. Mungkin tak ubahnya laba-laba yang pernah saya lihat membuat jejaringannya di sudut-sudut dan langit-langit rumahku. Jika seperti itu keadaannya, maka kesimpulannya sudah jelas. Sayalah yang lalai. Lalai dalam memperkirakan bahwa segumpal kotoran ternyata tak lebih dari setitik debu yang jika dibiarkan terus menerus akan berkelompok dan menjadikan pemandangan di rumah sayapun tak bersih lagi.
Memasuki bulan Ramadhan ini , kita mempunyai suguhan istimewa yang mendahului sahur pertama untuk berpuasa. Yaitu "hidangan" teror bom dan bahan bakar minyak. Hal yang pertama, selain mengundang perhatian dari seluruh kalangan dunia, juga menimbulkan anggapan pada masyarakat luas bahwa negeri kita adalah lahan bagi hidupnya satu bangsa yang telah disarangi kelompok teroris. Mungkin tak ubahnya laba-laba yang pernah saya lihat membuat jejaringannya di sudut-sudut dan langit-langit rumahku. Jika seperti itu keadaannya, maka kesimpulannya sudah jelas. Sayalah yang lalai. Lalai dalam memperkirakan bahwa segumpal kotoran ternyata tak lebih dari setitik debu yang jika dibiarkan terus menerus akan berkelompok dan menjadikan pemandangan di rumah sayapun tak bersih lagi.
Namun bom bukanlah debu seperti debu yang beterbangan di atas kepala saya ataupun seperti sarang laba-laba di dalam rumahku itu. Ia dapat menimbulkan ledakan debu yang sangat dahsyat. Tidak hanya kepada harta benda yang kita miliki, rumah kita yang berdiri di atas tanah negeri ini, tapi juga ledakan ketakutan di hati seluruh penduduk dunia.
Bahkan Mesir yang beberapa tahun terakhir dikenal sebagai negara yang cukup amanpun, ternyata eskalasi kekerasan di negeri itu belakangan ini cukup mencemaskan pula. Arab Saudi juga sampai sekarang masih dalam pertarungan melawan kelompok garis keras yang bersembunyi di negara itu. Begitu pula di Marokko, juga Cassablanca yang menjadi saksi bisu aksi antikemanusiaan ini.
Saya tidak pernah mengerti mengapa tindak kekerasan kini semakin menjadi-jadi justru ketika peradaban semakin menua. Seingat saya, pijakan analisis yang terkait dengan masalah terorisme ini adalah masa terjadinya tragedi 11 September tahun dua 2001, empat tahun yang ada di hadapan jika kita berjalan balik menghampiri peristiwa itu.
Setelah masa itu, ada dua perasaan yang saling "menikam" hati umat Islam. Pertama, rasa duka karena tragedi itu mengorbankan rakyat yang tidak bersalah. Kedua, rasa suka karena mereka--pelakunya--menganggap sebagai ekspressi perlawanan umat Islam terhadap Amerika yang selama ini selalu memojokkannya. Kedua perasaan yang saling menikam itu meninggalkan bekas yang sama saja: luka. Rasa suka seperti yang bagaimana jika aksi berdarah berarti bersekongkol dengan kejahatan ?. Namun pada perjalanan selanjutnya, rasa duka itupun terkalahkan dengan rasa suka setelah Amerika menyatakan perang terhadap kelompok Osama bin Laden yang bersarang di Afganistan. Aksi protespun memenuhi negara Islam. Bahkan aksi-aksi protes ini menobatkan seorang Osama sebagai "pahlawan Islam".
Ketika Amerika menghadapi Uni Sovyet di Afganistan, untuk menaklukkan Sovyet, Amerika pernah juga melakukan hal yang sama, yaitu bekerja sama dengan garis keras Islam yang juga melibatkan Osama. Karena mempunyai keinginan yang sama, maka terjalinlah kerja sama yang rapi untuk menghancurkan musuh bersama saat itu, yaitu Sovyet. Oleh karena itu, ketika kelompok Osama yang dulunyapun dilatih Amerika untuk menghancurkan Sovyet kini berbalik menyerang Amerika, maka penamaan yang tepat untuk kondisi itu tak lain adalah senjata makan tuan. Silang kepentingan yang menjadi pemainnya.
Mari kita bedah perkembangan teror yang terakhir ini banyak menghantam umat Islam sendiri. Ada perbedaan antara koalisi umat Islam dan kelompok garis keras yang dilakukan ketika Amerika menyerang Osama, dengan koalisi yang dilakukan Amerika dan garis keras untuk menghadapi Sovyet. Perbedaannya ada pada tujuan dan sokongan kekuatan. Untuk menumpas "musuh" sebesar Amerika perlu kekuatan tangguh secara militer dan ekonomi. Sedangkan "koalisi tak bersenjata" antara umat Islam dan garis keras tidak mumpuni, lambat launpun melemah dan kemudian hancur. Umat Islampun "menginjak" figur seperti Osama, dengan bermunculannya slogan dimana-mana bahwa Osama merusak citra Islam.
Di sisi lain, kalangan garis keras yang merasa dikhianati, menuduh negara-negara Islam bekerja sama dengan musuh. Aksi kekerasanpun mulai dialamatkan kepada mereka, termasuk Arab Saudi, Maroko, Mesir dan kami Indonesia. Kitalah yang selalu menjadi sasaran kekecewaan siapapun dan apapun terhadap perputaran waktu yang senantiasa mengandung kejadian, peristiwa dan yang kemudian menjadikannya sebagai sejarah.
Sekarang tentang saudara seibu kita disini. Keputusan pemerintah untuk mencabut subsidi bahan bakar minyak dan membagikan dana kompensasinya dalam bentuk bantuan langsung secara tunai kepada rakyat telah mengalihkan isu politik yang sensitif tentang hal itu, menjadi isu yang sangat teknis di lapangan. Ketika bantuan tunai dana kompensasi BBM itu sedang dibagikan kepada seluruh rakyat, antrian warga yang sedemikian panjang membuat kondisi fisik saudara kita menjadi lemas dan akhirnya pingsan dalam barisan rakyat miskin. Bahkan ada yang pingsan dan tak tertolong lagi hingga menemui ajalnya. Ada pula diantara kita yang mengomel karena tidak dapat menahan diri untuk bersabar menghadapi situasi di lapangan. Bahkan seorang nenek di Jogjakarta nekat menerjunkan dirinya ke dalam sungai untuk bunuh diri saja karena sudah frustrasi dengan urusan penerimaan kartu kompensasi BBM itu. Jika takut bunuh diri tapi tidak takut membunuh yang lainnya, seseorang di negeri inipun dapat dengan mudah menghilangkan nyawa orang lain di luar dirinya hanya karena faktor emosi. Seorang ketua RT (rukun tetangga) di daerah Jambi kabupaten Bungo, tewas dibunuh salah seorang warganya yang emosi karena korban tidak mendaftarkan warga tersebut sebagai warga miskin penerima dana kompensasi BBM.
Ada lagi pernik yang lucu. Di Sulawesi tengah kabupaten Donggala, ada keluarga yang menolak di daftar sebagai warga miskin karena malu dengan anggapan itu. Yah, istilahnya biar miskin yang penting sombong. Ini menyulitkan badan pusat statistik disana. Karena selain kurangnya waktu untuk pendaftaran dan tenaga pendata, juga kondisi geografis yang sulit dijangkau. Untuk mencapai daerah pegunungan dan kepulauan di sana harus naik kuda, bahkan hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki.
Kalau ada warga yang malu dianggap miskin dan menolak bantuan tunai tersebut--padahal memang miskin keadaannya--ada lagi keluarga yang keadaannya cukup layak namun mengaku miskin supaya bisa mendapatkan bantuan itu. Ada pula diantara kita yang mengajukan protes jika tidak didaftar sebagai warga miskin, karena kemiskinan adalah identitas rakyat di negeri ini. Kita khawatir jika tanpa identitas kemiskinan itu, pemerintah tidak dapat mengenali kita lagi...
Padahal, penentuan kriteria keluarga miskin inipun sebenarnya tidak luput dari persoalan tentang bagaimana variabel yang disebut miskin itu, jika dikaitkan dengan tingkat penghasilan keluarga. Ada sebuah keluarga yang rumahnya dibangun dengan sistem gotong royong--seperti arisan pembangunan rumah-- sehingga kondisi rumah yang ditempatinya tampak layak. Padahal jika ditinjau dari besarnya penghasilannya perbulan, mereka tergolong miskin.
Ada lagi yang berkesan seperti bantuan salah alamat. Dana kompensasi BBM dikirim kepada keluarga yang tergolong mampu, sehingga bantuan tunai itu bukan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari , tapi malah digunakan untuk membeli baju baru buat lebaran. Ada kepala desa yang dihajar karena urusan pembagian subsidi tunai langsung itu, namun ada pula kepala desa yang diam-diam ketahuan menyunat uang bantuan itu hingga 20%. Ini semua terjadi memang karena buruknya pengamanan dan kontrol kita selama di lapangan.
Dan yang paling memprihatinkan, semua ini terjadinya justru pada bulan Ramadhan. Bulan yang seharusnya tepat untuk sebuah kontemplasi yang manis pada diri setiap umat Islam.
Rakyat di negeri ini selalu terpapar sebagai model dari dua realita hidup: Islam dan kemiskinan. Kemiskinanlah yang menobatkan dirinya menjadi ibu dari semua keturunan dan anak cucu persoalan di negeri ini. Agama yang tidak mampu menggerakkan umatnya untuk mengamalkan ibadahnya dalam hidup bermasyarakat, diibaratkan sebagai bapak yang lama kelamaan menjadi impoten karena setiap hari ibu selalu mengomel tentang urusan dapur. Dan bapakpun mulai banyak berdiam diri karena sudah pusing tak menemukan lagi cara jitu untuk menenangkan ibu yang selalu menuntut penghasilan yang memadai, sebagai landasan kebutuhan hidup.
Posted by Cisca at 5:24 PM
Saturday, October 15, 2005
Air Mata
Izinkanlah kami, rakyat miskin, untuk memeras airmata darah. Itulah satu-satunya yang kami punyai, tinggal. Tidak, tidak. Kami rakyat miskin tidak menangis lagi. Kami hanya meminta izin untuk tetap sengsara disebabkan ketidak becusan kami dalam berburu nafkah. Jangan cambuk lagi kami dengan kasih sayang, cambuklah kami dengan penderitaan sepuluh tahun lagi, duapuluh tahun lagi, limapuluh tahun lagi, supaya kami, rakyat miskin, terus belajar bagaimana bertahan di segala cuaca.
Ketika menyadari bahwa setiap hari kami sangat kesukaran dalam mengatur uang belanja kami yang cupet, kami sadar, semakin mempersulit kerja siapapun yang mencoba menolong kami. Ya, kami menjadi beban. Beban yang berat sekali bagi siapa saja yang memikul kami.
Bagaimana kemungkinannya jika kami mengajukan eutanasia saja. Sekitar separo dari penduduk negeri ini, rakyat miskin, bisa dieliminasi supaya beban yang menyebabkan semuanya menderita bisa berkurang dalam sekejap. Tak ada gunanya memelihara rakyat miskin. Disamping sangat menghambat moderinisasi, rakyat miskin juga sangat boros dalam melahap kekayaan bangsa.
Kenaikan harga BBM memang fatal. Kami, rakyat miskin, ditempeleng telak. Kami terkapar. Ada saja anak-anak kami yang mencoba bunuh diri karena tidak mampu membayar yuang sekolah. Tidak tanggung-tanggung, 27.000 murid sekolah di Bogor terancam putus sekolah. Dewasa ini, kami yang jumlahnya ribuan, macet sekolahnya. Lalu menggelandang mencari pekerjaan apa saja. Kami juga menjadi pemulung, pengemis, penjambret, pencuri, perampok, pemerkosa, pembunuh, agen dari segala kerusuhan dan huru-hara. Pernah dengar sopir taksi yang dibunuh dan duitnya dijarah?. Itulah kerja kami. Kami membunuh kami, karena hanya dengan jalan itu kami bisa hidup.
Mitsubishi hengkang dari kebun kita dan memilih berinvestasi di Thailand, yang menyebabkan kami mampus. Berapa ribu karyawan yang kena PHK?. Tanpa dibunuhpun kami sudah tewas. Nah, beban dari yang berwajib berkurang dalam mengurus kami, setelah kami mundur dari dunia ramai. Alangkah mudahnya mengurangi derita. Barangkali sebentar lagi menyusul Honda, Hyundai, KIA, Toyota, Daihatsu, Suzuki, apa susahnya. Perusahaan besar datang dan pergi sesuka hati. Seperti datang dan perginya awan yang membentang di langit yang dapat diharapkan menjadi hujan.
Kami, rakyat miskin, memang sering bikin ulah yang menyebabkan para investor tidak tenang hidupnya. Yang berwajib tidak memperbaiki semua itu karena memang tidak mampu. Rasa aman, rasa tidak digerogoti, sudah sangat berat untuk ditanggulangi. Memang menyelenggarakan konferensi, kongres, muktamar, dan rapat-rapat jauh lebih memikat karena ringan, namun duitnya banyak, daripada menjaga para investor itu dari segala rongrongan.
Musim semi ekonomi Indonesia telah tiba, yang menikmati tentulah hanya para petinggi dan elite politik. Meski terdengar kata-kata mutiara: "Pesta yang buruk adalah pesta tanpa mengajak kaum miskin", tolong jangan ajak kami ke pesta, sebab itu cuma basa-basi yang sudah disobek dari lembar buku-buku pelajaran bagi orang-orang beriman. Orang-orang beriman sudah memiliki buku-buku baru yang lebih cocok.
Apalah arti musim semi ekonomi bagi rakyat miskin?. Semuanya itu cuma pembicaraan yang tidak mampu kami pahami. Yang kami butuhkan hanyalah yang serba konkret. Jika kami sakit beri kami obat. Jika lapar, beri kami makanan. Kalau sedih, hibur kami. Tapi, itu semua sudah tamat. Yang kami perlukan cuma eutanasia. Nah, kerjakan sekarang, mumpung penderitaan kami belum bertambah-tambah. Sekitar seratus delapan puluh juta jiwa bakal lenyap sekelebatan. Itulah pengertian yang selama ini kami yakini.
Kami tahu, beban berat tidak bisa dipikul terus menerus tanpa dipunggah dari pundak. Ayo, beristirahat. Kami berteduh di bawah pohon besar untuk melepas lelah dan peluh yang mengucur. Kami susun kembali karung-karung besar beban yang menggunung di sisi kami ketika kami lelap. Kami bermimipi sejenak: Mimpi tentang anak-anak yang kami lahirkan yang menempuh hidup di kemudian hari. Anak-anak ceras dan berbakti yang tetap saja digarong oleh masa depannya.
Andai kami bisa membentengi keturunan kami dari segala kerusuhan dan saling menerkam lewat mimpi kami ini. Ah, mimpi adalah godaan yang kami bangun sendiri dengan perih. Waktu jaga sudah kembali, haruskah kami terus bermimpi dan tak kembali lagi ke bumi. Alhamdullillah. Hidup hanya sepenggal catatan kusam yang tidak dibaca lagi. Kesanalah segala kesedihan berlabuh sampai kapal rusak dan tak mampu melaut lagi. Kami hanya rakyat miskin yang setiap saat dilupakan. Yang boleh dianggap tak pernah ada. Robeklah catatan dan kamipun lenyap.
Segala pasang surut APBN, harga minyak, dan para investor tak juga tertarik untuk mengadu untung di sini karena bahaya mengancam di setiap sudut kota, itu kesalahan kami, rakyat miskin, yang tidak memahami seluk-beluk citra dari segala penampilan. Kami sudah pasrah dengan segala tangan yang terikat ke belakang. Gusur kami, usir dan hardik. Penggal!, maka kepala kamipun menggelinding.
Kami, rakyat miskin, tinggal punya air mata darah. Seperti yang sudah diumumkan oleh Tsunami, Buyat, demam berdarah, flu burung, Polio, raskin, maupun tanah longsor dan banjir. Semua keterbukaan sudah tertutup bagi kami. Sampai disini riwayat kami. Jangan diperpanjang lagi derita yang hanya meninabobokan. Kami letih.
Konyol kami tak mampu melepaskan beban sendiri tanpa bantuan siapapun. Segalanya pernah ditulis. Segalanya pernah dikenang. Untung bagi kami yang kami hadapi hanyalah sisa-sisa kekuatan dari masa lampau yang sungguh tak sakti mencoba memberi nyawa kami. Yang papa, yang sengsara. Keadilan, kemakmuran, dan kebenaran, meski bagaimanapun pernah kami cecap, sedikit. Selamat tinggal.
Posted by Cisca at 5:14 PM
Tuesday, October 4, 2005
S e n y u m
Mengapa para koruptor yang tertangkap dan diadili tampak tersenyum manis?. Kenapa?. Boleh jadi hanya para psikolog yang tahu persis, mampu mengorek rahasia senyum mereka. Namun demikian, bolehlah kita menduga-duga arti senyum manis para jawara penilap uang negara itu.
Kemungkinan para koruptor meyakini bahwa uang negara yang berada di bawah kekuasaannya adalah uangnya. Mereka meyakini bahwa gaji cupet hanya mengantar keluarga menuju jurang kehancuran, sehingga harus diburu upaya-upaya radikal untuk mengatasinya. Mereka meyakini bahwa kedudukannya sebagai pejabat merupakan berkah yang memberi peluang untuk memperkaya diri sendiri, sementara negara tidak mungkin mampu menjamin kesejahteraan rakyatnya. Mereka meyakini bahwa setiap orang adalah koruptor, sehingga apa salahnya untuk tidak berbeda dengan sesamanya. Mereka meyakini bahwa bagi Indonesia sudah tidak ada harapan lagi melewati krisis dasamuka di negeri ini, sehingga setiap pejabat harus cukup bijaksana untuk mengambil tindakan-tindakan seperlunya untuk memperlambat kehancuran itu dengan menggerogotinya perlahan-lahan, supaya tidak sakit-sakit amat sekaratnya.
Ya, di Indonesia, hanya orang gila tidak korupsi. Jadi, setiap orang jadi tertuduh korupsi. Jika setiap orang jadi tertuduh koruptor, betapa sehatnya orang Indonesia. Hanya orang-orang sehat yang mampu korupsi. Jika seseorang sakit-sakitan, korupsinya tidak meyakinkan sehingga tidak pantas mendapat sebutan koruptor.
Lebih-lebih lagi, segala tindakan para koruptor mengatasnamakan dan demi kejayaan bangsa dan negara. Dus, tak akan ada penghalang lagi dalam melaksanakan cita-cita itu. Untuk bangsa dan negara, segala daya harus habis-habisan disumbangkan. Jika tidak, sungguh tak pantas disebut koruptor. Begitulah, setiap koruptor berlomba untuk berjasa bagi bangsa dan negara. Dengan demikian, mereka harus tampak tersenyum manis supaya memikat segenap rakyat.
Senyum Abdullah Puteh, gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, tampak pipinya terangkat montok dan manis sekali, jauh lebih manis daripada senyum yang ia berikan kepada istrinya. Senyum itu begitu telak menonjok kita hingga kita terkapar, masih juga ia menambah celetukan "Emangnya gue kagak tau kalo korupsi loe lebih gede!". Memang, kita harus mengakui bahwa korupsi kita jauh lebih gede ratusan kali daripada dia yang cuma tiga milyar rupiah lebih sedikit. Senyum yang sinis dan begitu tampak bijaksana tak membawa-bawa nama kita secuilpun. Bahkan, ia sudah bersumpah di bawah kitab suci Al Quran (yang kita tentu takut melakukannya) bahwa ia tidak bersalah dan sama sekali tidak melakukan tindakan korupsi.
Dalam senyum sehari-harinya ketika masih memegang jabatannya, ia tidak segitu manisnye. Khusus dalam peristiwa yang bersejarah itu, ia telah memberikan senyumnya begitu syahdu sehingga kita bagaikan mengalami pencerahan. Rasanya, jika kita tak mampu mengendalikan diri, kita akan serempak berteriak menyambutnya, " Korupsi kami jauh lebih gila!"
Senyum Mulyana W. Kusumah yang merebak ketika ia diseret oleh petugas, meski tampak lelah dan kuyu, namun begitu penuh pengertian atas segala sesuatu yang penuh rahasia itu. Ia yang paling muda dan bersedia menjadi martir, tentu hal yang itu merupakan sikap hidup yang penuh keteladanan. Ia mahfum, bahwa jika uang yang amblas sekitar 90 milyar rupiah, bagaimana mungkin seseorang yang bisa menyelamatkan seluruh jajarannya cuma minta 150 juta rupiah. Kan mustahil.
Apakah kita punya keberanian untuk menjadi martir, menjebakkan diri di sarang macan dengan resiko yang begitu besar. Karir dan keluarga hancur demi kebenaran. Dibanding Puteh dan Mulyana, kita cuma macan kertas. Secara mental dan tingkah laku, kita ini tak lebih dari jiwa budak mental kere, dan hal itu tampak begitu jelas bagai siang bolong dalam senyum Puteh yang penuh pelecehan terhadap jiwa kita. Betapa lemahnya kita!.
Sementara itu, tataplah senyum sepuluh orang bekas anggota DPRD Solo (1999-2004) yang dikerangkeng dalam kasus Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2003. Senyum mereka penuh kebanggaan diri. Senyum mereka yang menohok dada kita dengan penuh kesadaran diri. Kesepuluh orang itu tampak tersenyum ngobrol santai di balik kerangkeng yang bersih, yang bukan tidak mungkin memaki-maki kita dengan: "Bangkai kalian!".
Sungguh, betapa kerdil kita dalam mengikuti gerak hidup yang rutin, miskin dan menyedihkan. Kita membiarkan tubuh dan jiwa terseok-seok tanpa mampu membela dan meningkatkan diri untuk sekedar hidup pantas di tengah kemewahan yang melangit. Menapaki zaman gila, zaman bangsat, dimana kejujuran jadi tinja yang menempel di aspal jalanan sehingga banyak orang kecipratan sampai belepotan dan bau itu dibawa kemana-mana. Bau busuk yang tanpa kita sadari mencoba menjunjung hidup secara adil dan manusiawi, yang hasilnya cuma menggelikan di mata para paksasa yang memamah biak batang-batang kayu gelondongan.
Dan senyum kita, sungguh senyum yang tidak dibuat-buat, meski menjengkelkan karena tampak begitu tolol. Begitu tolol di hadapan para penguasa dan pejabat yang sangat lihai memainkan perannya dalam memanipulasi nilai-nilai yang kita agungkan sebagai penjelmaan ilahiah.
Masih banyak ragam senyum dari sejumlah senyum yang belum tampak di dalam layar monitor. Masih harus menunggu berapa lama lagi. Senyum para raksasa yang gigi-giginya sebesar gajah, tentu senyum yang sangat berbahaya bagi keselamatan hidup kita, bangsa dan negara. Kita, rakyat kecil yang ketakutan bisanya cuma menangis. Namun, tangis rakyat kecil adalah tangis kesejatian. Tangis kesejatian yang tak mungkin dimiliki para raksasa yang sudah terlanjur kepentok jalan buntu.
Posted by Cisca at 4:32 PM