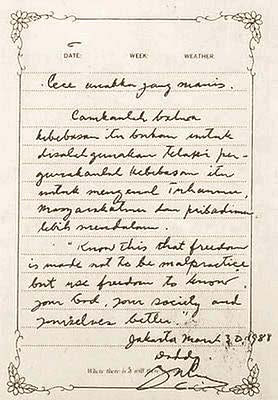Ketika seorang anak bertanya," Mengapa ibu menikah dengan laki-laki yang menjadi ayahku, Bu?", sebuah gugatan terhadap laki-laki sedang terjadi. Sang anak merupakan saksi dari serangkaian kekerasan yang dialami oleh ibunya. Mungkin si anakpun tidak mengerti, mengapa ibunya begitu tegar mempertahankan perkawinan itu. " Demi anak-anak ", kata sang ibu setiap kali ia mendapat pertanyaan yang sama.
Laki-laki yang menjadi suami dan ayah dari anak-anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan telah menjadi awal dari jalan panjang kehidupan seorang perempuan. Dalam perkawinan itu, perempuan mengalami kebaikan juga kemalangan. Perkosaan hak reproduksi, penindasan, trafficking, bahkan pembunuhan karakter dan cita-cita terjadi secara kasat mata dan terselubung.
Anak yang bertanya dan menggugat keabsahan institusi itupun menjadi korban berikutnya, karena nilai-nilai dan norma yang dibangun di dalamnya mengondisikan suatu kepasrahan dan kepantasan seorang perempuan. Sebagai perempuan seseorang disadarkan dan bahkan dipaksakan tentang betapa bedanya ia dibandingkan dengan lelaki, baik dalam hak maupun kewajiban. Peningkatan status seorang perempuan seperti status keluarga, tidak berarti inisiasi atas martabat perempuan terjadi dengan sendirinya.
Kartini pun memulai hidup baru yang tidak pernah diidealkannya setelah ia menikah dengan sang bupati, yang menyebabkannya melupakan impian-impian seorang idealis. Sangkar emas rumah tangga ini kemudian menempatkan Kartini kembali menjadi perempuan kebanyakan, tidak seperti yang ia tulis dalam surat-suratnya.
Kalau perkawinan kemudian menjadi suatu akhir dari seluruh mimpi dan awal dari malapetaka, mengapa seorang perempuan harus kawin?. Bukankah ia juga perlu diberi hak untuk hidup membujang dan memilih mewujudkan cita-citanya sekaligus membantu mewujudkan cita-cita kaumnya?. Perempuan sebaiknya dilarang kawin, dan itu bukan tanpa alasan. Paling tidak ada alasan yang bisa disebut.
Perkawinan dapat menjadi penjara bagi kaum perempuan yang menjauhkannya dari dunia publik. Perkawinan itu menjadi suatu lembaga yang mengesahkan penindasan kecerdasan dan pembunuhkan kreativitas perempuan. Rutinitas dalam keluarga telah mendikte dan membatasi bukan hanya partisipasi perempuan dalam kegiatan publik, tetapi juga ide-ide kreatifnya. Dari perempuan lebih sering kita mendengar alasan anak sakit, menemani anak ujian atau pembantu pulang kampung, ketimbang laki-laki. Laki-laki tidak merasa harus bertanggungjawab untuk kegiatan yang bersifat domestik. Kecenderungan ini meninggalkan ruang yang begitu sempit untuk perempuan berkiprah dalam matra kegiatan yang lebih produktif dan yang menyaratkan konsentrasi dalam olah pikir. Ruang artikulasi dan aktualisasi diri perempuan atas kapasitas yang dimilikinya sangat terbatas.
Kalaulah perkawinan itu menjadi penjara yang mematikan kreativitas proses berpikir yang sangat potensial yang dapat dilakukan oleh kaum perempuan, mengapa ia harus mengorbankan dirinya untuk masuk ke dalam penjara itu ?. Rumah tangga harusnya menjadi tempat perempuan menemukan identitasnya, sementara suami tidak dapat menjadi mitra yang memfasilitasi rencana-rencana yang dimiliki perempuan.
Rumahtangga adalah ranah domestik yang menjauhkan kaum perempuan dari hak-hak yang secara hukum berlaku dalam publik. Perkawinan telah menyebabkan proses domestikasi perempuan yang mengembalikan perempuan ke ruang domestik. Banyak sekali perempuan yang telah menjalani hidupnya di ruang publik yang bekerja secara professional, kemudian memutuskan meninggalkan pekerjaan mereka dengan alasan " ikut suami ", atau berhenti bekerja setelah memiliki anak pertama. Adanya mas kawin dalam perkawinan menjadi satu persoalan, karena dalam wilayah kebudayaan tertentu mas kawin memiliki nilai tukar atau pengganti yang disampaikan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Pertukaran semacam ini berimplikasi pada perpindahan hak atas perempuan ke keluarga suami dimana perempuan tersebut secara kultural tunduk kepada laki-laki atau bahkan pada keluarga laki-laki.
Proses domestikasi ini mendapat pengesahan secara sosial dan legal. Payung hukum tidak efektif dalam dunia domestik, sehingga kaum perempuan atas nama istri atau ibu rumah tangga tidak mendapatkan proteksi yang cukup dalam lingkungan domestik ini. Berbeda dengan ruang publik dimana hukum berlaku secara lebih efektif. Kekerasan yang dialami perempuan dalam rumah tangga misalnya, diperlakukan sebagai persoalan internal, kurang relevan secara sosial, sehingga praktek dan kepatuhan hukum tidak masuk sampai ke ruang domestik tersebut.
Perkawinan menjadi tempat yang melucuti seluruh kedirian perempuan. Perkawinan menyebabkan perempuan kehilangan dirinya karena ia harus menjadi bagian dari entitas yang lebih luas. Dalam proses ini potensi perempuan selain tersembunyi, juga kediriannya dikorbankan menjadi bagian dari suatu tatanan yang tidak ikut dia bangun. Pengorbanan semacam ini sering kali membuat kaum perempuan kesepian, kehilangan kawan dan dunia perempuan, karena ia harus hidup dalam dunia yang dikonstruksikan oleh para lelaki atau institusi-institusi yang berpihak pada lelaki.
Institusi perkawinan tidak semestinya menjadikan perempuan terkungkung dan kehilangan jati diri sebagai individu. Institusi itu dapat saja menjadi dukungan bagi pengembangan minat dan bakat yang memungkinkan aktualisasi diri dalam dunia publik. Banyak sekali perempuan yang beruntung dalam perkawinannya, namun lebih banyak lagi yang tidak mendapatkan dukungan dan justru setelah perkawinan terjadi, diri perempuan tenggelam dalam rutinitas dan kebosanan tiada ujung.
Alasan-alasan itu agaknya menegaskan perlunya pertimbangan seksama tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh perempuan, laki-laki dan lembaga-lembaga yang terkait, sebelum sebuah perkawinan dapat dilangsungkan. Apa cukup perkawinan itu atas kesepakatan dua orang ( laki-laki dan perempuan ) saja ?. Apakah pasal-pasal dalam buku nikah cukup menjadi pegangan hukum bagi jaminan hak-hak perempuan ?.
Bagaimana kita dapat melindungi perempuan dari kemungkinan perkosaan dalam rumah tangga atau pengingkaran terhadap kebutuhan strategisnya?. Jika kemaslahatan tidak dapat dicapai dan dijamin dengan adanya perkawinan, mengapa peristiwa itu disahkan?. Jika perkawinan itu menghilangkan identitas diri kaum perempuan, sebaiknya suatu perkawinan perlu digagalkan.
Sayangnya, dulu kita tidak sempat melarang sang bupati menikahi Kartini. Kalaulah Kartini tidak menikah, mungkin anak-anak tidak perlu lagi bertanya pada ibunya, " Mengapa ibu menikah dengan laki-laki yang menjadi ayahku, Bu?".
Friday, April 21, 2006
Haruskah ?
Posted by Cisca at 11:21 PM
Sunday, April 16, 2006
Granada - Gaza
 Bangsa Israel, kaum Yahudi, tidak luput dari kisah pengusiran. Fenomena terakhir terlihat di depan mata, sebagian warga Israel harus keluar dari kandang perkampungan Gaza. Mereka diusir dan dikucilkan. Padahal bagi bangsa Yahudi, pengusiran dan pengucilan adalah sebuah dislokasi spiritual juga fisikal. Peristiwa pengusiran dari perkampungan Gaza membuka kenangan lama, peristiwa pengusiran bangsa Yahudi dari daerah Granada, Spanyol.
Bangsa Israel, kaum Yahudi, tidak luput dari kisah pengusiran. Fenomena terakhir terlihat di depan mata, sebagian warga Israel harus keluar dari kandang perkampungan Gaza. Mereka diusir dan dikucilkan. Padahal bagi bangsa Yahudi, pengusiran dan pengucilan adalah sebuah dislokasi spiritual juga fisikal. Peristiwa pengusiran dari perkampungan Gaza membuka kenangan lama, peristiwa pengusiran bangsa Yahudi dari daerah Granada, Spanyol.
Waktu itu, tepatnya 2 Januari 1492, pasukan raja Ferdinand dan Ratu Isabella, dua penguasa Katolik, yang pernikahannya mampu menyatukan dua kerajaan Iberia kuno, Aragon dengan Castile, berhasil meluluhlantakkan negara kota Granada, satu wilayah pertahanan terakhir kaum muslim di daerah Kristen. Inilah awal pembersihan penduduk muslim dan Yahudi dari daratan Eropa.

Tiga bulan kemudian, 31 Maret 1492, Ferdinand dan Isabella menandatangani Perintah Pengusiran ( Edict of Expulsion), yang dibuat untuk membersihkan Spanyol dari bangsa Yahudi. Orang-orang Yahudi waktu itu diberi dua alternatif: memilih dibaptis masuk Kristen atau dideportasi.
Ada 80 ribu warga Yahudi migrasi ke Portugal, 50 ribu lainnya mengungsi ke kerajaan baru Islam, Utsmaniyyah. Di daerah kekuasaan Islam, kaum Yahudi seperti halnya warga Kristen, diberi status dzimmi (minoritas yang dilindungi). Status ini bentuk perlindungan militer dan sipil bagi mereka yang menghormati hukum dan supremasi negara Islam.
Dan sebagian yang lain, memilih masuk Kristen dan menetap di Spanyol, karena mereka sudah terlanjur jatuh hati dengan "al-Andalus" ( nama lain kerajaan Islam di Spanyol).
Orang-orang Yahudi yang menyeberang ke agama Kristen seringkali disebut "converse" ( umat yang berpindah agama), tapi komunitas Kristen lebih sering menjuluki mereka "marrano" (babi). Sebagian warga bekas Yahudi, karena ketidaktahuan mereka, dengan bangga memilih sebutan terakhir, "marrano", babi.
Sepenggal kisah di atas, ingin mempertegas ritual kehidupan bangsa Israel yang tidak lepas dari pengusiran dan pengucilan. Pengusiran dan pengucilan dari perkampungan Gaza, juga merupakan dari ritual dari kehidupan bangsa Yahudi. Hanya saja, kini mereka harus keluar dari wilayah yang dihuni sebagian besar penduduk muslim, yang bertahun-tahun mereka singgahi tanpa mau mengakui identitas mereka yang sebenarnya.
Satu ciri khas bangsa Yahudi, bangsa urban, warga Israel ini, memang unik. Mereka merasa berkuasa di berbagai wilayah, bebas dari jebakan-jebakan kekuasaan dan seringkali mengendalikan takdir mereka dengan logika dan penalaran sendiri.
Orang-orang Yahudi, dalam lintas sejarah dan bacaan-bacaan sejarah, merasa hidup dalam isolasi agama dan selalu meyandarkan diri pada takaran rasional. Mereka mengabaikan kitab suci, dan hampir pasti tidak memiliki rentetan pengalaman ritual "hukum suci" dari Taurat. Anehnya, cerita-cerita kaum Yahudi ini, kemudian dijadikan mitos.
Seperti halnya mitos soal warga Israel yang melarikan diri dari Mesir dan melewati Laut Merah. Cerita ini kemudian dijadikan mitos yang dikaitkan dengan cerita-cerita lain mengenai ritual inisiasi, pengarungan samudera, dan terbelahnya laut menjadi dua oleh para dewa untuk membuka dunia baru bagi bangsa Yahudi.
Pendeportasian warga Yahudi dari Gaza, pada titik yang lain, adalah satu ritus panjang kehidupan kaum Yahudi. Mereka tidak memiliki tempat singgah dan menyebar ke berbagai daratan di seantero dunia. Hal lain, di luar kesepakatan damai Israel - Palestina, pengusiran warga Israel sebenarnya untuk menutupi wajah bopeng Amerika yang selama ini jadi benteng terakhir Israel. Amerika, tentu saja, malu kepada dunia karena tidak mampu menaklukkan "anak asuh"nya sendiri. Jalur kehidupan sebuah bangsa memang tidak selalu ditentukan oleh diri sendiri, tapi ia juga bisa ditentukan oleh bangsa lain.
Hal lain, di luar kesepakatan damai Israel - Palestina, pengusiran warga Israel sebenarnya untuk menutupi wajah bopeng Amerika yang selama ini jadi benteng terakhir Israel. Amerika, tentu saja, malu kepada dunia karena tidak mampu menaklukkan "anak asuh"nya sendiri. Jalur kehidupan sebuah bangsa memang tidak selalu ditentukan oleh diri sendiri, tapi ia juga bisa ditentukan oleh bangsa lain.
Itulah sepenggal potret kehidupan warga Israel, juga Palestina, dimana identitas kehidupannya tercerabut oleh kepentingan-kepentingan negara-negara besar yang selalu merayakan demokrasi sekaligus mematikan demokrasi itu sendiri.
Posted by Cisca at 11:16 PM
Thursday, April 13, 2006
C i l a - C i l i

"Banyak orang yang cerdas!. Banyak orang yang pandai!. Tapi kecerdasan dan kepandaian itu hanya diperuntukkan untuk tujuan yang keji-keji belaka. Itu banyak terjadi dan kau tak boleh memasukkan dirimu ke dalam golongan orang yang seperti itu." ( Pramoedya Ananta Toer )
Pendidikan adalah segala-galanya bila ingin maju. Maju harkat pribadinya, maju nasionnya, maju peradabannya. Itulah salah satu dari banyak hal yang diangankan Pram.
Lewat novel Burunya, Pram mengatakan bahwa kemajuan bisa dicapai jika unsur mitos yang mencandra akal dan feodalisme yang membungkam rasio, bisa tertusuk tumpas dengan pendidikan. Sebab kedua paham itu menghalangi seorang manusia untuk merebut martabatnya sebagai manusia yang maju dan merdeka karena dipaksa oleh sebuah hierarki yang dibentuk oleh sistem feodalisme raja-raja.
Sebuah adegan ketegangan pendidikan dan feodalisme diperlihatkan Pram dalam salah satu paragraph di Bumi Manusia : " aku mengangkat sembah sebagaimana aku lihat dilakukan punggawa terhadap kakekku dan nenekku dan orangtuaku. Dalam mengangkat sembah, serasa hilang seluruh ilmu dan pengetahuan yang kupelajari tahun demi tahun belakangan ini. Hilang indahnya dunia sebagaimana dijanjikan oleh kemajuan ilmu. Sembah pengagungan pada leluhur dan pembesar melalui perendahan dan penghinaan diri sampai sedatar tanah kalau mungkin…uh! Anakcucuku tak kurelakan menjalani kehinaan ini."
Karena tak rela menjalani kehinaan, maka Pram mengangankan bahwa semua pribumi kelak bisa mengecap pendidikan yang tinggi. Walaupun kita tahu Pram tak sanggup menjejaki angan-angan itu. Ia hanya lulusan SMP kelas 2 di Surabaya sebab sekolah keburu bubar karena serangan balatentara Jepang. Lalu di Jakarta pada usia 17-20 tahun, sembari bekerja di kantor berita Jepang, Domei, Pram mencoba mendaftar ikut kuliah filsafat dan sosiologi di sekolah tinggi Islam yang diasuh Dr.Rasjidi dengan bayaran 25 rupiah dari hasil menjual kemeja kaos putih dan biru muda yang baru duakali dikenakannya.
Tapi hasilnya nihil. Dan ia pun mengembara mencari pengetahuan dari buku-buku, dari klipingan koran dengan cara otodidak. Lalu himpunan dan data-data itu menjelma menjadi karya-karya besar lagi terpuji dan mengukuhkan namanya menjadi sastrawan dunia.
"Walaupun seorang yang enggak tamat SMP, saya ini doktor lulusan Amerika." ujar Pram bangga sembari tertawa.
Menurutnya tidak mesti orang belajar dengan membaca buku. Belajar bisa dengan mengamati, menghafal, memperhatikan, mendengarkan. Banyak belajar ilmu pengetahuanpun tidak menjamin orang menjadi kreatif. Bagi Pram, orang yang cedas dan kreatif adalah yang pandai menarik kesimpulan dari ilmu dan pengetahuannya dan pengalamannya.
Dalam beberapa kesempatan, Pram sungguh prihatin dengan tergusurnya pendidikan yang mengajarkan watak yang mandiri, kuat dan cerdas, menjadi pendidikan yang terkomersialisasikan.
Alih-alih ingin menggapai kualitas pendidikan yang baik dengan harga terjangkau. Para pelaku di dunia pendidikan kita lebih sibuk dan berpeluh menaikkan ongkos daripada menaikkan kualitas pendidikan. Hasilnya, watak yang dihasilkan dalam dinding-dinding kelas sekolah tak lebih dari watak manusia-manusia lama yang masih berada di alam agraris dan feodal.Watak ingin menjadi pegawai negeri, birokrat.
Ada banyak alasan mengapa profesi ini menjadi cita-cita, walau gajinya relatif kecil. Salah satunya adalah status pegawai negeri menjanjikan jaminan kepastian hidup dan masa depan.
Pendidikan kita, diakui atau tidak, selama ini memang tidak serius mencetak manusia-manusia yang berjiwa berdikari dan mampu merintis sebuah kerja mandiri dan tak harus menjadi budak bagi orang lain atau menjadi manusia kuli. Pendidikan kita seakan menjangkar dan memperluas kesadaran serta meluapkan keinginan bahwa bila lulus kelak akan menjadi pegawai negeri. Paling tidak menjadi pelamar pekerjaan dengan menenteng ijazah kesana-kemari dan mengantri panjang untuk mengambil formulir kartu kuning di depnaker ketika bursa kerja dibuka secara massal.
Para praktisi pendidikan barangkali menolak asumsi bahwa pendidikan menjadi terdakwa dalam hal ini. Namun kenyataan berbicara jujur bahwa sistem pendidikan kita tidak merangsang manusia untuk berkarya dan mandiri, melainkan mencetaknya sebagai manusia benalu dalam masyarakat. Buktinya, setiap tahun meruyak sebarisan panjang angka pengangguran sarjana.
Penting untuk menilai pengalaman secara seksama dengan ketajaman mata selidik. Sebab setiap pengalaman yang tidak dinilai, baik oleh dirinya sendiri ataupun orang lain, akan tinggak sesobek kertas dari buku hidup yang tidak punya makna. Padahal setiap pengalaman adalah fondasi kehidupan.
Oleh sebab itu, tegas Pram, belajarlah menilai pengalaman sendiri dan membentur-benturkannya dengan lingkungan tempat dimana pengalaman itu tumbuh. " Beras menjadi putih bukan hanya karena tertumbuk alu, tetapi karena pergeseran dengan sesama beras karena tumbukan alu." kata Pram mengutip ucapan salah satu srikandi pergerakan nasional awal abad 20, Siti Soendari.
Bila penuntasan kasus korupsi dan penyelewengan sulit diberantas, maka ini bukan keanehan. Rendahnya usaha itu bukan hanya terkait dengan begitu rumitnya jaringan korupsi, aparat hukum dan negara yang mungkin tak becus, tapi juga terkait dengan masalah kesadaran. Kesadaran itu adalah kesadaran hidup menjadi ambtenaar di republik yang sudah sesak dengan pegawai negeri ini.
Banyak orang yang menjadi meester atau doktor hanya karena orangtuanya mampu membiayai atau karena diongkosi oleh orang lain. Ini bukan hal yang mengagumkan. Hanya orang yang bisa mengangkat dirinya sendiri menjadi doktor atau meester atau insinyur dengan tenaga dan kekuatannya sendiri, itulah yang patut mendapat pujian. Itu tandanya orang-orang yang betul-betul punya kemauan, mempergunakan kecerdasan, kekuatan, dan kepandaian yang dimilikinya.
Titel akademi bukan tujuan manusia, itu hanya alat . Sama saja seperti pisau, mobil, pacul untuk menggampangkan orang dalam mencapai cita-citanya. Andaikan seorang anak gembel yang hidup di gubuk dan makan tak ketentuan bisa mendapat gelar akademi, itu baru hebat.
Jika kita masih percaya pada lembaga pendidikan, maka yang mesti dilakukan adalah mendorong lembaga-lembaga tersebut untuk membekali diri dengan kekuatan mendidik orang-orang dalam asupan pengetahuannya untuk menjadi manusia berwatak, mandiri, mau bekerja keras, serta memupuk daya saing dalam praktek bermasyarakat. Dan semua watak itu sulit kita dapatkan dalam mental orang-orang yang sedari dini bercita-cita menjadi kaum ambtenaar yang pemalas, miskin kreatifitas, dan kerjanya hanya rebutan proyek!.
Posted by Cisca at 7:04 AM
Monday, April 10, 2006
C a n t i k
Pembantu yang baru di rumah saya cukup berpotensi menimbulkan bibit kecemburuan di diri saya. Wajahnya mencolok berbentuk kotak dengan tulang pipi yang tinggi, dan kulit yang mulus. Matanya berbentuk almond sempurna, bibirnya merekah indah.
Saya curiga dia melarikan diri dari kampungnya ke Jakarta karena menjadi kembang desa di sana. Tentunya dia banyak menyusahkan kehidupan orang karena menjadi rebutan terlalu banyak lelaki. Sedangkan kalau saya yang berada di posisinya di desanya, saya sudah bisa membayangkan bisa-bisa orang-orang di sana langsung bedol desa.
Menjadi cantik tentunya berbeda dengan menjadi pandai, atau apa yang orang bilang sebagai inner beauty, bahwa kecantikan di dalam tentu akan memancar keluar dan membuat kita tampak lebih menarik. Untuk sekarang, saya justru ingin berkutat dengan penampilan luar itu.
Selama ini saya merasa risih jika tiba-tiba predikat " cantik " dilekatkan pada nama saya. Hidung saya kembang kempis, pipi saya terasa terbakar, dan mata saya hanya mampu menatap lantai. Saya hampir tidak pernah merasa cantik. Lebih jauh lagi, saya selalu mengecamkan pada diri sendiri untuk tidak usah repot-repot melongok di cermin untuk mengecek penampilan. Kalau tidak menghembuskan nafas panjang-panjang, maka giliran bibir saya yang maju karena saya selalu kecewa mendapati apa yang ada di dalam bayangan cermin itu.
Satu detik saya mabuk dengan penampilan diri sendiri, tentu saja hal pertama yang terjadi adalah saya bertemu model jelita yang mempelototi saya dari atas sampai bawah. Dan karena kepala saya hanya sepinggangnya, saya kurang bisa mendengar apa komentarnya tentang saya.
Saya mempunyai banyak sekali teman berwajah elok. Banyak. Dan sungguh elok. Saya sering termangu memandangi setiap jengkal wajah mereka dan mendadak ingin meraih obat serangga. Saya juga yakin teman-teman saya kadang mengalami hilang ingatan, akibatnya mereka memuji penampilan saya pada suatu hari. Sembari tersenyum saya terbata-bata mengucapkan terimakasih, namun di dasar hati saya yakin mereka lupa minum obat, dan karenanya, berhalusinasi.
Ketika saya bercermin dan pantulannya membuat saya terdiam dan terkagum-kagum, saya tahu di luar sana saya hanya membutuhkan waktu maksimal lima menit untuk paling tidak menumpahkan saus makanan ke baju saya bagian dada. Satu menit yang lalu, boleh saja saya menjadi perempuan mempesona di kamar kecil itu, tapi ketika saya melangkah keluar dengan dagu terangkat naik lebih dari biasanya, mata saya hampir buta akibat seorang perempuan lain yang begitu terang benderang karena luar biasa cantiknya.
Saya tahu akan ada hari-hari dimana saya merasa tidak ingin ke luar rumah dan tidur seharian saja lalu mimpi menjadi secantik Daria Werbowy misalnya.
Dan mungkin yang saya butuhkan di hari-hari seperti itu adalah sekedar mengingat ujaran teman-teman saya bahwa, ...ya, saya bisa tampil cantik. Contohnya, ketika kehujanan, dengan mantel rajutan dan rambut di kuncir ekor kuda serta kacamata tebalpun, saya masih saja mendapat pujian itu.
Maka mungkin saya tidak usah menjelma menjadi burung merak yang senantiasa telihat pongah dengan penampilannya, dan yang lebih penting, saya juga tidak usah memirip-miripkan diri dengan burung unta yang lebih sering menenggelamkan kepalanya ke dalam tanah karena malu hati. Yang harus saya ingat adalah ketika orang lain tampil lebih cantik dari saya, tentu itu bukan akhir dari segalanya. Saya mencoba percaya bahwa saya tetap cantik dengan cara saya sendiri. Dan kalau masih saja saya memutar-mutar mata, tidak puas dengan penampilan diri sendiri, saya selalu bisa berkonsultasi dengan pembantu saya tadi. Saya yakin ia bisa mendidik saya untuk menjadi kembang desa berikutnya.
Posted by Cisca at 4:04 PM