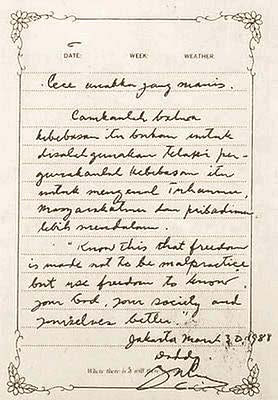Yandenur adalah seorang tuna makna. Kehidupannya tidak punya arti. Pekerjaan tidak punya, keluarga tidak punya, pulang ke rumah orangtua malu dianggap gagal. Bertahun-tahun ia berkelana ke rumah teman-teman masa pendidikannya di padepokan Pmks. Disitu ia berdiam berminggu-minggu, kadang kala sampai bulanan. Teman-temannya di eks padepokan Pmks bukan orang berada. Bagaimana bangsa perperadaban tinggi seperti Jerman bisa membantai 6 juta manusia ?. Pertanyaan ini mengganggu pikiran seorang mahasiswa S3 di Universitas Harvard. Namanya Steven Milgram. Seperti Yandenur yang taat pada sang Guru, para algojo Nazi juga patuh pada perintah atasan yang berwenang. " Befehl ist befehl ! ", kata mereka.
Mereka sekedar punya pekerjaan tetap dan walaupun agak pas-pasan, masih sanggup menampung teman lama berminggu-minggu. Pengangguran berkepanjangan membuat keresahannya meningkat dan harga dirinya merosot. Seringkali ia berpikir tentang kegunaan hidupnya. Pada saat-saat itu ia mulai mengarungi jurang-jurang depresi jiwanya.
Pada suatu hari seorang yang baru dikenalnya menghampiri dan menyampaikan pesan bahwa ia dicari seorang yang bernama Sul. Keesokan harinya Sul datang dan memberinya uang sebanyak Rp.50.000,-. " Dari pendoa Pdst", kata Sul. Ada sejam Sul duduk mengobrol ringan tentang 1001 soal dalam kehidupan. Lalu Yandenur diajak makan di warung dekat rumah dimana ia menginap. Tak lama kemudian Sul minta diri dan berjanji akan berkunjung lagi. "Kapan-kapan", katanya. Yandenur termenung memikirkan peristiwa yang baru dialaminya. Uang Rp.50 ribu diraba-raba di kantong kemejanya.
Seminggu kemudian Sul datang lagi dengan uang Rp.50.000,- lagi. Sebulan kemudian Yandenur bergabung dengan kelompok pendoa Pdst. Di situ sudah ada 8 pemuda. Mereka mendaraskan pujian dan lewat tengah malam berdoa utama. Pada tengah malam ke 100, Yandenur diantar oleh 8 pemuda ke tengah ladang. Di sana Sang Guru telah menanti. Di bawah sejuta bintang di langit, dengan kitab suci di atas kepala, Yandenur melintasi jembatan transeden, dan dalam kesucian masuk ke lingkaran gaib. Ia bersumpah taat sampai mati.
Pada 1 0ktober setahun lalu Indonesia menerima deklarasi perang dari Bali. Dalam deklarasi itu tergambar suatu ruang besar restoran yang hancur lebur. Pecahan kaca berhambur campur bata, genteng dan plafon yang remuk. Atapnya ambruk. Di dinding tertempel potongan daging, tipis-tipis seperti dipotong untuk membuat dendeng. Darahnya masih mengalir kental, merah tua. Di kaki kursi tersangkut tangan kanan perempuan yang masih memegang tas. Pada bagian yang tersobek dari dadanya tampak daging memasir putih, tanpa darah.
Suara merintih bersaing dengan jerit orang yang belum dibunuh. Seorang laki-laki tersenyum malu memandang orang yang bergegas mau mengangkatnya. Kepalanya masih belum sempat terangkat, ia sudah keburu tewas. Orang yang mau mengangkatnya heran. Baru setelah tangannya lepas dari punggung jenazah, ia sadar bahwa pundak orang yang mau ditolongnya sudah dikoyak serpihan bom.
Pernyataan perang Yandenur ditujukan kepada bangsa Indonesia, tanpa pandang bulu apakah ia seorang Islam, Kristen, Budha, Hindu, Konghucu. Kebetulan saja mayoritas yang terbunuh beragama Islam. Yandenur tidak ambil pusing akan hal itu. Instruksinya jelas : Pukul sasaran yang mengakibatkan kerugian besar, publisitas global , kerusakan parah dan jangka panjang : Bali!.
Yang tetap mengherankan bagi Milgram adalah, mengapa dalam tabrakan antara ketaatan dan hati nurani, yang menang adalah ketaatan. Mengapa ?. Untuk desertasinya, Steven Milgram melakukan penelitian sosial / psikologi di Universitas Yale. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa kebanyakan orang tidak terlalu perduli pada penderitaan orang yang disiksanya bila ia mengerti tujuan penyiksaan, dan disuruh menyiksa oleh figur-figur yang mengesankan berwenang.
Antara penelitian Milgram dan Yandenur tidak banyak perbedaan. Yandenur harus terlebih dulu dibuat mengerti akan penjelasan Sang Guru tentang tujuan perang. Baru kemudian ia akan menaati perintah perang tanpa memperdulikan apakah korbannya itu orang Indonesia atau orang asing, sesama muslimkah atau kafir.
Di Indonesia, ada banyak Yandenur. Mereka tidak beroperasi dalam suatu vakum. Medan sosial / politik mereka saat ini menunjukkan karakteristik tertentu. Secara makro kita menyaksikan dimainkannya suatu mitos di forum domestik maupun global : "Islam di Indonesia itu moderat dan amat toleran. Yang ekstrim itu hanya suatu minoritas kecil". Ini merupakan suatu mitos, karena yang menjajakannyapun tak percaya akan kekecilan para ekstrimis. Kalau memang kecil, mengapa tidak dikecam dan difatwakan secara jelas kecamannya ?. Takutkah akan kehilangan dukungan politik " si kecil " ?.
Mitos ini juga sudah dibubarkan oleh penelitian kuantitatif yang mengukur seberapa jauh gairah demokrasi di kalangan aliran-aliran besar Islam di Indonesia, yaitu mayoritas moderat dan toleran yang dikumandangkan dimana-mana. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa di kalangan aliran-aliran besar tersebut, banyak sekali kantong-kantong besar kaum skriptualis fundamental. Secara makro, kita saksikan juga bahwa elite politik Indonesia enggan menggelorakan konsepsi Pancasila, ide dasar negara Republik Indonesia.
Mereka takut akan dihubungkan dengan paksaan azas tunggal zaman Soeharto, dan dengan demikian mengambil resiko kehilangan dukungan ekstrimis yang dikatakan " minoritas kecil " itu. Aparatur negara juga ragu mencegah tindakan sepihak atas nama hak asasi dan agama kaum ekstrimis. Keraguan itu sebagian disebabkan oleh ketidakpahaman tentang hak asasi, mana yang tidak boleh dilibas dan mana yang harus dilibas karena melanggar hak asasi orang lain.
Untuk sebagian lagi, sebab musababnya berada di sektor politik real. Gerakan ekstrim dipakai untuk tujuan politik jangka pendek pencari posisi kenegaraan. Dalam menanggapi gerakan-gerakan garis keras, NU ( Nahdatul Ulama) dan Muhamadiyah setengah-setengah. Polisi ragu, TNI dilarang berkutik, elite politik berlagak lupa Pancasila sebagai konsepsi yang melandasi dasar negara.
Konteks semacam ini adalah surga buat gerakan-gerakan ekstrim. Mereka bertindak sepihak tak ada yang melawan kecuali protes kecil disana-sini. Tercatatlah kemenangan kecil. Protes mereda, mereka sekali lagi bertindak sepihak. Suara protes masih ada, tapi mulai mengecil. Polisi diam di tempat. Politisi takut menyebut Pancasila.
Tambahkan pada konteks tersebut berita misalnya tentang latihan perang di hutan Jawa Tengah. Lalu ada khotbah di Jakarta Utara yang menjamin bahwa setiap rupiah sumbangan umat akan digunakan untuk menjatuhkan pemerintahan RI yang sekuler. Ratusan gereja ditutup. Ahmadiyah diserang dimana-mana. Islam liberal harus dilarang.
Dari aspek kontekstual inilah selayaknya kita membaca 11 fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang bersifat eksklusif dan bernada agresif. Kondusifkah atau tidak konteks semacam ini bagi teroris dan terorisme Indonesia.
Ada 1000 Yandenur yang dengan berdebar hati menunggu gilirannya untuk dibaiat, untuk dikirim ke luar negeri menuntut ilmu perang, untuk melaksanakan perintah suci Sang Guru. Saya persilakan mereka menjawab pertanyaan itu.
Nama tokoh dan cerita hidup Yandenur hanya fiktif.
Tuesday, October 17, 2006
N o s t a l g i
Posted by Cisca at 5:16 PM