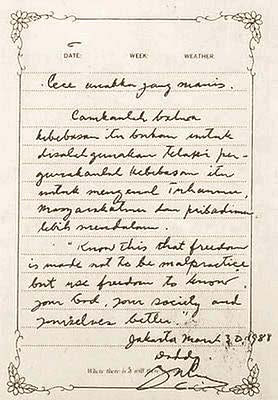Partai Amanat Nasional (PAN) lahir di tengah gejolak kebutuhan reformasi politik di Indonesia. Wajar bila ada tuntutan agar PAN tidak terjebak ke dalam kesalahan parpol masa lalu. Akan menjadi celaan sepanjang sejarah bila PAN justru tenggelam, hanyut di tengah sekuen politik yang seharusnya direformasi.
3 Kesalahan---kalau tidak mau disebut penyakit kronis--- parpol di Indonesia selama ini adalah eksklusivisme, personalisasi institusi dan keengganan untuk menjadi kekuatan oposisi yang berujung pada ketidakmampuan parpol melaksanakan fungsi paling dasarnya. Sejauh ini kita saksikan kesulitan parpol mengembangkan basis konstituen sebagai akibat masih kentalnya pandangan yang sangat eksklusif, baik pada tataran elite maupun aktivis dan simpatisan mereka. Tiap upaya melebarkan basis konstituen ( yang merupakan kebutuhan satu partai moderan) selalu dilawan dengan sikap ideologis dari elite manapun simpatisan parpol. Contohnya PDIP. Saat konsep marhaenisme hendak dilonggarkan supaya bisa merekrut konstituen kelas menengah bahkan kelas atas, segera direspons oleh core supporter mereka.
Kesulitan ini bertambah karena kegagalan banyak parpol membangun sistem dan mekanisme kerja yang baku, yang menyebabkan virus personalisasi institusi ( yang biasa ditemui pada fase awal perkembangan parpol ) tetap ada, bahkan terkesan makin menguat. Figur pimpinan partai identik dengan partai itu sendiri. Dengan konstelasi seperti ini, mudah bagi pimpinan parpol untuk mentransformasikan kehendaknya menjadi kehendak institusi. Bahkan ( dalam banyak kasus ) pandangan dan harapan pribadi figur sentral dimaknakan sebagai ideologi bagi aktivis dan simpatisan parpol.
Parpol dengan mudah dapat dijadikan elite untuk berkuasa. Orientasi ideal parpol direduksi hanya pada merebut kekuasaan. Tidak dengan kesiapan kemampuan mengelola kekuasaan itu, apalagi berpikir untuk apa kekuasaan itu diberikan kepada mereka. Bila dalam politik salah satu indikator "kehebatan" politikus adalah merangkul lawan menjadi kawan, maka nafsu berkuasa memudahkan pengendali parpol masuk dalam lingkaran kekuasaan. Lupa bahwa penguasa "harus ditantang" agar tidak terjadi kesewenang-wenangan kekuasaan. Inilah arti penting oposisi di Indonesia. Ini pula yang tidak pernah terjadi, sehingga selalu terjadi kecenderungan pemusatan kekuasaan di setiap rezim politik di Indonesia. Ini tantangan PAN sebagai partai reformis.
Ketika Prof. Amien Rais---sebagai tokoh sentral dalam PAN---tidak mau dicalonkan lagi dan dia juga tidak mencalonkan siapa-siapa, sikap ini menunjukkan bahwa masalah PAN adalah regenerasi dan revitalisasi organisasi. Agak aneh kedengarannya, sebagai parpol baru PAN sudah merasakan kebutuhan regenerasi. Padahal beberapa parpol lama tidak merasakan ini dan terjebak dengan pemimpin yang " itu-itu saja". Tapi bila dilihat faktor usia dan kebutuhan Pemilu 2009, jelas regenerasi PAN harus dilakukan segera bila tetap ingin memelihara tren positif pada Pemilu 2004 kemarin.
Beberapa petinggi PAN sudah berusia "kepala 5" ( 50 tahun ketas) bahkan "kepala 6" ( 60 tahun keatas). Pemilih pada Pemilu 2009 nanti didominasi oleh generasi yang lahir tahun 1970-an and 1980-an, yang saat ini berusia 30-40 tahun. Konkretnya, ada jarak satu generasi di anatara mereka yang masih ingin dipilih dan pemilih. Padahal pola pikir dan tindak mereka berbeda, sebagai produk perbedaan semangat zaman.
Pada sektor ini PAN tidak perlu risau, karena yang berbeda hanya umur. Soal kemampuan intelektual, penalaran antara elite PAN tidak jauh berbeda. Kalaupun dicari-cari, perbedaannya ada pada "jam terbang" dari generasi lapis pertama ( Amien Rais dkk) dengan generasi lapis kedua (sebut saja Didiek Rachbini dkk). Tinggal dicari siapa di antara tokoh muda PAN memiliki jam terbang terbanyak memimpin organisasi, tapi tidak terkait dengan struktur rezim dan kekuasaan saat ini.
Masalah PAN terberat justru pada revitalisasi dan reposisi PAN dalam konstelasi politik nasional. PAN butuh mengembangkan basis konstituen. Ideologi mereka harus dirumuskan kembali secara cermat agar pendukung utama ( core supporter) tidak lari ketika PAN mengembangkan basis dukungan. Ini bukan pekerjaan mudah. Mayoritas lapisan kedua elite PAN adalah mereka yang tidak terlibat dalam proses kelahiran partai ini. Apalagi fakta menunjukkan banyak elite lapis kedua yang pendiriannya masih belum teruji saat berhadapan dengan manisnya aroma kekuasaan. Adanya tokoh PAN yang menjadi tim sukses SBY-Kalla di saat Amien Rais menjadi pesaingnya menunjukkan bahwa solidaritas PAN dan integritas elite lapis kedua masih kurang tangguh untuk menghadapi pemilu 2009.
Memperhatikan konstelasi politik nasional saat ini, posisi terbaik PAN untuk kebutuhan Pemilu 2009 adalah berperan sebagai kekuatan oposisi. Ini satu ruang kosong yang justru diharapkan publik ada aktor berperan di situ. PAN sudah melakukannya, misalnya bersama dengan beberapa partai lain, PAN menolak kenaikan harga BBM.
Posisi ini harus terus dipelihara. Bila tidak, nasib PAN bisa terseret oleh nasib Presiden SBY di pilpres 2009 nanti. Sebab, ada kader PAN di jajaran kabinet SBY yang seolah konfirmasi dukungan PAN pada presiden SBY. Logika ini bila tidak dikoreksi secara cerdas justru akan merugikan PAN. Koreksi cerdas di sini adalah mencermati setiap langkah pemerintahan SBY-Kalla dan menawarkan perspektif tandingan yang bisa dikaji secara rasional oleh masyarakat. Sekali lagi, Amien Rais sudah melakukannya. Saat berkampanye, pasangan Amien-Siswono mengangkat masalah illegal logging sebagai alternatif pendanaan APBN. Melihat angka kerugian negara sekitar 35 trilyun rupiah hingga 45 trilyun rupiah tiap tahun dari praktek haram ini, seharusnya PAN sudah bisa tampil dengan konsep tandingan.
Menyimak konstituennya, ada optimisme yang tinggi bahwa PAN bisa melakukannya. Masalahnya, mampukah para elite lapis kedua mengeliminasi aspek negatif dari gaya kepemimpinan "one man show", sebagai bentuk lain dari personalisasi institusi yang juga terjadi di parpol lain. Kalau elemen ini tidak berhasil dieliminir, maka jangan heran bila segala keunggulan yang saat ini ada di tangan mereka akan sirna begitu saja.
Friday, May 18, 2007
Partai Amanat Nasional (PAN)
Posted by Cisca at 2:29 PM
Friday, May 11, 2007
Mei Kelabu dan Jejak Reformasi
Bulan Mei 1998 adalah bulan yang amat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada 12 mei 1998, beberapa mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak. Kemarahan dan anarki menyusul pada 13-14 Mei di Jakarta dan Solo. Kondisi politik nasionalpun menegang. Klimaks dari kejadian-kejadian tersebut adalah turunnya Pak Harto dari jabatannya sebagai presiden pada 21 Mei 1998.
Sejarah Indonesia segera berbelok drastis. Orde baru---setidaknya dari sudut pemerintahan--- telah berakhir. Pemerintah baru hadir dengan kebijakan baru yang sebagian besar amat berbeda dengan masa sebelumnya. Meski pemerintahan Habibie berisi kolaborasi antara "orang-orang lama" dan "baru", tetapi hakikat kebijakan (politik) yang diambilnya relatif sama sekali baru.
Satu hal yang membedakan pergantian "kekuasaan" dari Soeharto kepada Habibie dengan ketika Soeharto menggantikan Soekarno, adalah "nasib politik"nya. Pak Harto sakit dan sudah sangat sepuh. Proses pengadilannyapun tampaknya tidak akan pernah "tuntas". Kalaupun ada rekonsiliasi, mungkin model Korea Selatan yang lebih pas dilakukan kepada Soeharto. Diadili lantas diampuni.
Yang penting ada sebuah proses pembelajaran bagi bangsa. Pak Harto, bagaimanapaun dikecam banyak orang, telah menunjukkan itikad baiknya dengan turun dari panggung kekuasaan dan tidak melanjutkan "Soehartoisme". Susah untuk membuktikan bahwa Soeharto mengacaukan proses reformasi dan demokratisasi di Indonesia, setelah ia lengser. Pengadilan sejarah akan menilai bagaimana posisi dan perannya selama ini.
Soal lain yang lebih penting adalah jalannya reformasi itu sendiri. Reformasi adalah "kata ajaib" yang menyatukan berbagai kalangan pada 1998, untuk mendorong percepatan kejatuhan pemerintahan Orde Baru. Yang terjadi kemudian bukannya reformasi yang evolusioner, tapi revolusioner, khususnya dalam bidang politik. Reformasi politik terkait dengan proses demokratisasi. Hingga kini perubahan-perubahan mendasar telah terjadi, dengan dilakukannya amandemen UUD 45 sebanyak 4 tahap. Boleh dibilang proses reformasi politik di Indonesia telah memberikan optimisme tersendiri, walaupun---dalam banyak kasus eksperimentasi politik yang direncanakan---terhadang oleh banyaknya kekhawatiran.
Reformasi di Indonesia pasca Orde Baru tidak lepas dari konteks "liberalisasi", baik politik maupun ekonomi. Kecenderungan proses demokratisasi di Indonesia kini adalah demokrasi politik yang liberal. Begitu pula dengan konteks lingkungan ekonomi dan pilihan-pilihan kebijakan yang diambil, tampaknya tidak dapat lepas dari paradigma ekonomi pasar. Apakah dengan arah kecenderungan yang "liberal" seperti itu masa depan Indonesia dapat lebih terpastikan?. Tidak menjamin. Demokrasi liberal di dalam masyarakat yang plural membutuhkan sejumlah persyaratan. Tingkat keberhasilannya dapat dicapai dengan pemenuhan persyaratan-persyaratan itu, dan sejauh mana manajemen konflik mampu tercipta.
Salah satu syaratnya adalah tingkat konsensus yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini dapat dipahami, mengingat masyarakat yang plural terdiri dari beragam kelompok kepentingan yang bersentimenkan primordial. Tanpa adanya kesadaran dan aksi konsesual atas banyak persoalan bangsa, maka hanya akan menyulitkan proses manajemen konflik. Demokrasi membutuhkan pengelolaan atas banyak potensi konflik yang ada.
Menelusuri jejak reformasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari Peristiwa Mei 1998. Dari Peristiwa Mei dan peristiwa-peristiwa yang kemudian menyertainya, sesungguhnya banyak pelajaran yang dapat diambil. Pertama, perubahan membutuhkan pengorbanan. Para mahasiswa yang gugur dalam Peristiwa Mei, juga martir lain yang meninggal dalam kerusuhan 13-14 Mei tentu saja bukan tanpa makna. Mereka bukan sekedar victim, tetapi sudah menjadi bagian dari pemicu perubahan sejarah. Untuk sebuah perubahan, disadari atau tidak, diniatkan atau kebetulan, mereka telah "dikorbankan" oleh pergolakan zaman.
Kedua, reformasi ternyata lebih merupakan proses ketimbang hasil. Pergantian rezim kekuasaan bukan berarti akhir dari tujuan gerakan reformasi. Justru setelah rezim berganti, ragam permasalahan menyeruak. Kondisi tidak langsung membaik. Banyak hal mesti dibenahi dalam setiap rezim yang berganti-ganti. Reformasi adalah sebuah proses yang penuh tantangan di tengah kecenderungan demokrasi politik dan lingkungan ekonomi yang semakin liberal.
Ketiga, penguatan civil society dalam konstelasi politik secara makro mengalami kondisi pascaklimaks. Yang terjadi---pasca Orde Baru--- bukan penguatan civil society, tetapi kekuatan-kekuatan politik di luar itu, utamanya Negara (state) dan Pasar (market). Gerakan mahasiswa dan kalangan muda mengalami kelesuan kembali, seolah kehilangan momentum. Fenomena "gagal konsolidasi" terus terjadi pasca Orde Baru. Faksionalisme antar kekuatan kalangan mahasiswa dan pemuda (plus LSM) kelihatan makin meninggi, disamping lambat laun kalah popular dengan kekuatan partai-partai politik. Dan "tidak ada apa-apanya" dibanding kekuatan pasar. Wallahua’lam.
Posted by Cisca at 7:20 PM