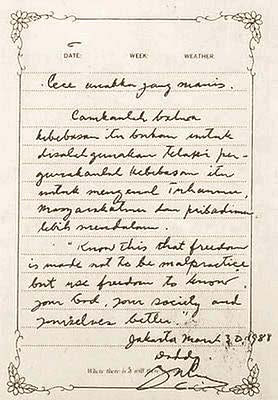Pada saat-saat menjelang dan berlangsung Sidang Istimewa MPR, sempat muncul pertanyaan : Quo Vadis, Indonesia?. Pertanyaan itu ditujukan kepada para elite politik yang sudah bertengkar memperebutkan arah mana yang mau ditempuhnya, dengan sama-sama mengibarkan alasan: demi masa depan Indonesia. Sementara rakyat kebingungan, karena melihat lajur dan jalur yang dipilih saling berbeda. Pertanyaan makin gencar dan tajam, tetapi hingga kini jawabannya belum ada.
Tidak terjawabnya pertanyaan itu karena semua pihak lebih suka memposisikan diri sebagai orang yang bertanya. Para pemimpin dan elite politik yang dituduh itu sudah sibuk cakar-cakaran. Pada gilirannya juga mengoper pertanyaan itu untuk dijawab oleh lawan-lawannya. Pertanyaan bukan lagi pertanyaan, tetapi senjata untuk melumpuhkan saingan, karena pasti tidak akan mampu dijawab.
Mengapa pertanyaan Quo Vadis begitu disukai?. Karena ketika pertanyaan diajukan, muncul subyek yang dianggap bertanggungjawab atau lebih bertanggungjawab daripada yang bertanya. Umumnya mereka para elite politik pemimpin juga. Merekalah yang sudah dipercaya rakyat akan menunjukkan arah dan cara mencapai tujuan. Tetapi fakta membuktikan bahwa para elite politik dan pemimpin itu lebih banyak bekerja untuk kelompok atau mungkin untuk dirinya sendiri daripada bangsa. Karena itu makin lama pertanyaannya cenderung berbunyi "Ngapain sih ente bawa kami kesitu?".
Ada semacam mosi tidak percaya kepada yang ditanya. Lebih dari itu ada pengingkaran dari yang bertanya, seakan-akan ia sendiri memang bersih. Tepatnya, ada semacam "pengampunan" kepada yang bertanya, seakan-akan ia sendiri tidak ikut campur mewarnai sejarah. Padahal ia berkubang dalam sejarah dan aktif main sabet kanan kiri kalau keadaan memungkinkan. Kadangkala tanpa sembunyi-sembunyi lagi, karena budaya malu sudah kuno. Pendek kata, kesalahannya hanya ada pada kelompok elite dan para pemimipin yang sudah ditanyai, bukan pada yang bertanya. Alhasil, pertanyaan sebenarnya bukan benar-benar pertanyaan, tapi usaha untuk mengelak. Dengan kata yang lebih lugas : lari!.
Perilaku yang sengaja ataupun tidak sengaja mengelak itu memang curang dan klise. Sudah waktunya dihentikan sekarang. Rakyat harus berhenti meng-Quo Vadis-kan para elite politik dan pemimpinnya. Sudah terlalu banyak kambing hitam, lama-kelamaan tidak jelas lagi siapa yang benar-benar mak nyainya. Lagipula kalau yang bersalah terlalu banyak, jadi seperti piknik saja.
Sudah waktunya kini rakyat harus menanyakan pertanyaan itu kepada diri sendiri. Artinya sudah waktunya menuding bahwa yang bertanggungjawab, yang terlibat adalah : rakyat. Karena apabila rakyat mendakwa diri sendiri, kelompok elite dan para pemimpin dengan sendirinya sudah di skip alias ditiadakan. Mereka sudah dianggap tidak lagi mempresentasikan kehendak rakyat. Sudah tidak pantas mewakili rakyat. Dan orang yang tidak mewakili entah karena tidak mampu, gagal atau berkhianat kepada tugasnya, tidak perlu lagi diperhitungkan.
Dengan kata lain, para elite dan pemimpin sudah tidak perlu masuk perhitungan lagi. Yang bertindak adalah rakyat, tanpa harus melalui elite dan pimpinannya, karena semuanya untuk kepentingan rakyat sendiri. Sistem perwakilan yang ditawarkan oleh demokrasi, untuk sementara "kurs"nya merosot sekali. Jadi apa boleh buat, abaikan saja. Kita kembali ke zaman pemerintahan kota, dimana rakyat memerintah dirinya sendiri.
Dengan menanyakan kepada dirinya sendiri: Quo Vadis Indonesia, setiap individu rakyat menjadi punya kewajiban harus menjawab dan tidak mungkin lagi mengelak bahwa ia tidak ikut dalam menentukan masa depan. Ini sangat penting, agar kelak tidak ada lagi semacam seminar/diskusi panel atau apapun namanya yang para pesertanya merasa tidak ikut andil dalam kesalahan masa lalu, sambil mengumbar kata-kata Quo Vadis kepada orang lain.
Apabila rakyat sebagai individu mulai bertanya kepada dirinya sendiri,"Quo Vadis Indonesia", masing-masing tidak melihat negara ini sebagai sebuah konsep kekuasaan lagi. Bukan konsep politis, tetapi konsep kebutuhan. Dengan memposisikan negara menjadi pengertian yang begitu naif, katakanlah konyol, jawaban terhadap Quo Vadis akan mudah. Aksioma ini bisa dijawab cepat, "Negara dibawa kemana saja, dipimpin oleh siapa saja, dengan bentuk pemerintahan yang mana saja, terserah. Asal lebih menjamin keamanan, ketentraman dan kesejahteraanku".
Dengan jawaban pribadi itu, mudah sekali misalnya, Paitem seorang tukang kebun--bukan nama sebenarnya--akan bilang, "Kalau begini caranya, dibandingkan dengan masa-masa sesudah reformasi, masih enakkan juga zaman Pak Harto." Jawaban yang boleh jadi sangat bertentangan dengan harapan para idealis yang memikirkan kehidupan negara yang lebih adil, lebih benar, lebih sesuai dengan tegak hukum dan hak asasi manusia. Tetapi kita mesti mengerti bahwa Paitem sudah mengambil kesimpulannya sendiri berdasarkan pemahamannya sebagai tukan kebun.
Saya berusaha menjelaskan kesimpulan Paitem itu tidak benar, karena keadaan lebih baik itu tidak bisa diukur dengan hal-hal permukaan saja. Kemerdekaan, keleluasaan dan hakikat demokrasi yang kita kejar-kejar sudah semakin dekat dibanding zaman Orde Baru. Paitem mendengarkan dengan sungguh-sungguh, manggut-manggut mengatakan mengerti dan setuju. Tapi besoknya, kalau pendapatnya ditanya lagi, tetap saja ia bilang bahwa di zaman Pak Harto keadaannya lebih baik.
Saya penasaran. Saya naikkan gajinya, saya berikan fasilitas yang lebih baik. Saya bantu sekolah anak-anaknya. Paitem mengucapkan terimakasih dan nampak senang, bahkan tangan saya dicium berkali-kali. Tetapi giliran mengemukakan pendapat, tetap saja ia bilang, zaman Pak Harto keadaannya lebih baik.
Disitu saya sadar. Rentang waktu sudah berbicara. Rakyat memerlukan bukti-bukti dalam satu kepastian yang teruji waktu. Dan itu mencakup semua nilai. Bukan saja kepastian hukum, tetapi juga kepastian emosional. Kepastian yang akan memberikan rakyat kesempatan untuk bekerja menekuni bidangnya agar bisa menyusun kehidupannya yang lebih baik di masa depan.
Kita sudah semakin hafal apa arti kelompok. Institusi massa itu adalah alat bersama untuk mengeroyok, mengepung dan bersolidaritas dalam persaingan kepentingan yang semakin tidak memungkinkan individu berjalan sendirian. Anggota masyarakat berkomplot untuk memperjuangkan nasibnya ( dan bukan negaranya) dalam organisasi, partai, aliran dan sebagainya dengan harapan bisa kebagian lebih banyak.
Mau tidak mau seorang pemimpin akan lahir untuk mewakili mengambil keputusan dan punya wewenang yang kemudian di ujung-ujungnya, kesewenang-wenangannya tidak bisa dibatasi. Praktis kebutuhan kelompok kembali tersulap menjadi kebutuhan individu. Konsep pemimpin sebagai individu yang mengabdi rakyat, tidak memerlukan proses lagi untuk otomatis terbalik menjadi individu yang diabdi rakyat. Saat itu (sekarang ini) apa masih perlu bertanya, "Quo Vadis Indonesia?".
Jawabannya harus tegas, "Kenapa tidak!". Justru inilah saat kita tetap bertahan untuk bertanya-tanya terus, "Quo Vadis, Indonesia?"
Wednesday, March 28, 2007
Quo Vadis, Indonesia?
Posted by Cisca at 7:11 PM